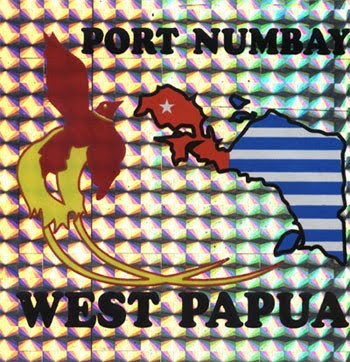PEMBUATAN ETANOL SECARA FERMENTASI DARI LIMBAH KULIT PISANG
OLEH
YUSUF PEKEI
JURUSAN KIMIA FMIPA UNHAS 2010
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Etanol adalah salah satu bahan kimia organik terbesar yang di gunakan pada industri-industri. Etanol dapat digunakan sebagai pelarut selain air. Alkohol, terutama etanol merupakan bahan penting pada perusahaan obat-obatan, minyak wangi, kosmetik dan bahan bakar. Etanol adalah cairan tak berwarna yang mudah menguap dengan aroma yang khas. Ia terbakar tanpa asap dengan lidah api berwarna biru yang kadang-kadang tidak dapat terlihat pada cahaya biasa. Sifat-sifat fisika etanol utamanya dipengaruhi oleh keberadaan gugus dan pendeknya rantai karbon etanol. Gugus dapat berpartisipasi ke dalam ikatan hidrogen, sehingga membuatnya cair dan lebih sulit menguap dari pada senyawa organik lainnya dengan massa molekul yang sama ( Rahman,A., 1994).
Produksi etanol di indoneia sebagian besar di lakukan melalui teknik fermentasi, karena proses ini di anggap paling sederhana. Bahan baku untuk proses fermentasi ini merupakan karbohidrat yang berasal dari bahan pertanian seperti ketela, jagung, tebu (molase) dan sebagainya. Etanol merupakan salah satu produk fermentasi yang banyak digunakan sebagai pelarut dan zat antara di industri farmasi dan kimia. Produksi etanol secara fermentasi umumnya menggunakan ragi dari spesies Saccharomyces dan Schizosaccharomyces. Fermentasi etanol oleh kedua spesies ini menghasilkan perolehan etanol yang tinggi. Pada saat ini fermentasi etanol di Indonesia umumnya menggunakan ragi Saccharomyces ( Rahman,A., 1994).
Perkembangan industri yang semakin meningkat dalam dekade terakhir ini akan tidak menutupi kemungkinan kebutuhan etanol akan semakin meningkat. Dengan demikian di butuhkan bahan baku pembuatan alkohol dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia sepanjang waktu yang mana bahan tersebut juga merupakan bahan makanan manusia. Padahal kebutuhan akan bahan makanan pun semakin meningkat pula seiring dengan tambahnya jumlah produk. Karena itu perlu di pikirkan sejak dini untuk mencari bahan-bahan alternatif yang dapat di jadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan etanol. Salah satu kemungkinan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan fermentasi terhadap kulit pisang, karena di samping banyak mengandung karbohidrat juga mempunyai aroma yang menarik. Adanya upaya pemanfaatan limbah pisang telah memperbanyak pilihan untuk mendayagunakannya dari sekedar sampah saja. Kulit pisang dapat di manfaatkan menjadi obat tradisional dan bahan kimia berupa asam asetat dan etanol. Untuk yang terakhir ini telah di lakukan penelitian awal oleh beberapa peneliti yang telah menunjukkan potensi di hasilkanya etanol (Rahman A., 1992).
Kulit pisang adalah salah satu bahan buangan (limbah) yang cukup banyak, yaitu sepertiga dari buah pisang yang belum di kupas, sesuai dengan data produksi pisang di Sulawesi selatan tahun 1995 sebanyak 194,668 ton. Kulit pisang ini belum di manfaatkan secara nyata, hanya di buang sebagai sampah belaka. Disamping itu untuk memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai bahan baku pembuatan etanol cukup banyak, namun tidak dimanfaatkan dengan baik tapi hanya di buang saja sebagai sampah
Pemanfaatan limbah kulit pisang sampai saat ini belum banyak di ketahui, apalagi untuk meningkatkan mutu serta penyebarluasannya. Pengkaji merasa perlu melakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana limbah kulit pisang dapat di manfaatkan sebgai bahan baku pembuatan etanol dengan cara fermentasi.
1.2 Maksud dan Tujuan Kajian Pustaka
1.2.1 Maksud Kajian Pustaka
Kajian ini bermaksud unutk mengkaji limbah kulit pisang sebagai bahan baku pembuatan etanol secara fermentasi.
1.2.2 Tujuan Kajian Pustaka
1. Mengetahui potensi limbah kulit pisang sebagai bahan dasar Untuk pembutan
etanol secara fermentasi
2. Mengetahui proses yang lebih baik untuk menghasikan etanol dari limbah
kulit pisang.
1.3 Manfaat Kajian Pustaka
1. Memberikan informasi mutu mengenai limbah kulit pisang lewat
pegolahannya menjadi etanol.
2. Memberikan informasih tentang alternatif cara pengolahan limbah kulit
pisang menjadi etanol.
1.4 Rumusan Masalah
Sejauh mana penelitian telah di lakukan mengenai peningkatan limbah kulit pisang sebagai bahan dasar pembuatan etanol dan bagaimanakah potensi produksi etanol dari limbah kulit pisang.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Uraian Umum Tentang Pisang
2.1.1 Klasifikasi Pisang
Pisang mempunyai tangkai buahnya terdiri atas 6 sisir sampai 12 sisir yang masing-masing terdiri 15 buah. Bentuk buahnya melengkung dengan bagian pangkal bulat. Warna daging buahnya kuning kemerahan tanpa biji. Empulur buahnya nyata dengan tekstur kasar. Rasanya manis, lama tanaman berbunga sejak anakan adalah 14 bulan. Sedangkan buah masak 164 hari sesudah muncul bunga.
Adapun klasifikasi pisang adalah sebagai berikut :
Regnum : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Subdivisio : Angiospermae
Klass : Monocotyledoneae
Ordo : Zingeberales
Famili : Musaceae
Genus : Musa
Sumber : Supriyadi, A. Satuhu, S., 1996
Buah pisang mempunyai kandungan gizi yang baik, antara lain menyadiakan energi yang cukup tinggi di banding dengan buah-buahan yang lain. Pisang kaya akan mineral seperti kalium, magnesium, besi, fosfor, dan kalsium, mengandung vitamin B; B6; dan C, serta mengandung serotonin yang aktif sebagai nitransmitter untuk kelancaran fungsi otak. Bila di banding dengan buah apel, nilai energi pisang bernilai lebih tinggi, yakni 136 kalori per 100 g, sedangkan buah apel hanya 54 kalori per 100 g. karbohidrat pisang mampu menyuplai energi lebih cepet dari pada nasi dan biscuit sehingga para atlet olahraga banyak yang mengkonsumsi pisang disaat jeda untuk merecherge energi mereka. Kandungan energi pisang merupakan energi instan yang mudah tersedia dalam waktu singkat sehingga bermanfaat dalam menyediakan kebutuhan kalori sesaat.
2.1.2 Komposisi Kulit Pisang
Unsur Satuan Jumlah
Air
Karbohidrat
Lemak
Protein
Kalsium
Fosfor
Besi
Vitamin B
Vitamin C %
%
%
%
mg/100 gram
mg/ 100 gram
mg/ 100 gram
mg/ 100 gram
mg/ 100 gram 68,90
18,50
2,11
0,32
715,00
117,00
1,60
0,12
17,50
Sumber : Munadjim 1983
Karbohidrat pisang merupakan karbohidrat kompleks tingkat sedang dan tersedia secara bertahap sehigga dapat menyediakan energi dalam waktu cepat. Karbohidrat pisang merupakan cadangan energi yang sangat baik bagi tubuh. Gula pisang merupakan gula buah yang terdiri dari gula fruktosa berindeks glikemik lebih rendah dibanding dengan glukosa sehingga cukup baik sebagai penyimpanan energi karena metabolismenya sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, pisang adalah alternatif terbaik untuk meyediakan energi di saat istirahat atau jeda, terutama pada saat otak sangat membutuhkan energi yang cepat tersedia untuk aktifitas biologis. Bagi orang yang bertubuh gemuk atau takut gemuk, pisang merupakan buah yang sangat baik untuk dikonsumsi sekalipun dalam jumlah yang banyak karena kandungan lemaknya masih lebih rendah dari pada apel, yaitu hanya 0,13% sementara kandungan lemak apel 0,3% (Suyanti. A., Supriyadi, 2008).
2.1.3 Tempat Tumbuh Tanaman pisang
Pisang termasuk tanaman yang gampang tumbuh karena bisa tumbuh di sembarangan tempat. Namun, agar produktivitasnya optimal, sebaiknya pisang di tanam di daerah dataran rendah. Ketingian tempat yang ideal untuk pertumbuhan pisang berada di bawah 1.000 meter dpl. Diatas kisaran tersebut, produksi pisang cendrung kurang optimal, waktu berbuah menjadi lebih lama, serta kulit buah menjadi lebih tebal. Iklim yang dikehendaki adalah iklim basah dengan curah hujan merata sepanjang tahun. Oleh karena itu, tanaman pisang raja memberikan hasil yang baik pada musim hujan dan hasil yang kurang memuaskan pada musim kemarau. Namun, hal ini bisa di atasi dengan memberikan pengairan pada musim kemarau.
Walaupun bisa tumbuh dan menghasilkan buah di lahan yang kritis, tanaman pisang tetap menghendaki kondisi tempat tumbuh yang subur. Di daerah beriklim kering antara 4-5 bulan, tanaman pisang masih tumbuh subur asalkan air tanah tidak lebih dari 150 cm di bawah permukaan tanah. Sebagai contoh di Sumbawa dan Timor, suatu daerah beriklim kering, pisang masih dapat tumbuh. Akar tanaman ini mampu memanfaatkan uap air dari dalam tanah dan menyimpannya dalam batang. Di daerah tersebut, batang pisang di gunakan sebagai sumber air minum ternak. Walau tidak meyukai tanah kering, pisang juga tidak terlalu menyukai air yang menggenag secara terus- menerus. Akar tanaman ini memerlukan drainase dan sirkulasi udara dalam tanah yang baik. Tak heran bila tanaman pisang yang tumbuh di tepi sungai yang airnya mengalir ke banyakan tumbuh subur karena sirkulasi udara dalam tanahnya berlangsung baik. Kedalaman air tanah yang sesuai untuk pisang yang tanam pada daerah beriklim biasa adalah 50-200 cm di bawah permukaan tanah. Sementara jenis tanah yang di sukai tanaman pisang adalah tanah liat yang mengandung kapur atau tanah alluvial dengan pH antara 4,5-7,5. Oleh karena itu, tak heran bila tanaman pisang yang tumbuh di daerah dengan tanah berkapur pertumbuhannya akan sangat baik, seperti di pulau Madura yang banyak memiliki bukit-bukit kapur (Suyanti.A.,supriyadi, 2008).
2.2 Mikroorganisme dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhannya
Ragi merupakan suatu bahan yang sangat penting dalam proses fermentasi. Tanpa penggunaan ragi sebagai sumber mikroorganisme, maka tidak akan dapat memperoleh hasil yang memuaskan bahkan dapat menyebaban kegagalan. Dalam hal ini mikroorganisme yang dapat digunakan adalah mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dalam jumlah yang besar.
Produksi etanol dari fermentasi bahan sisa makanan yang mengandung gula digunakan oleh khamir untuk pertumbuhannya pada suhu 25-33 oC, pH 4-5 dan masa peragian 2-10 hari. Ragi untuk tape merupakan campuran populasi, dimana terdapat spesies – spesies dari genus Aspergillus, Sacromyces, Candida, Hansenula sedangkan bakteri Acetobacter biasanya tidak ketinggalan. Genus-genus tersebut hidup bersama secara sinergetik, aspergillus dapat menyederhanakan amilum, sedang sacromyces, candida dan hansenulla dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lainnya. Acetobacter menumpang untuk mengubah alkohol menjadi asam cuka (Dwidjoseputro, D., 1989).
Proses ini terdiri dari tiga tahap yaitu pembuatan starter, induk peragian, dan peragian. Sebelum dimasukkan dalam tangki starter, khamir dikembangbiakkan di laboratorium dengan mencampur 50 g extract yeast, tetes 10o Brix satu liter dan ZA 1g, serta 1,5 – 2%. Media ini di masukkan dalam tabung reaksi kemudian di sterilkan dan dibuat agar miring. Khamir yang ada ditumbuhkan pada media ini selama 24 jam, kemudian di pindah ke tetes 7o Brix steril dengan pH 3,0 – 4,0 sebanyak 50 ml dalam Erlenmeyer dan diinkubasi selama 1-2 hari atau hingga kelihatan khamir tumbuh aktif, yang terlihat dengan munculnya gelembung-gelembung CO2. Berikutnya ditambahkan tetes steril 80o Brix sebanyak 1/3 volume semula. Penambahan pupuk yang di gunakan adalah 1% dari volume akhir setelah penambahan media. Bila kepekatan sudah turun menjadi 4o Brix, tambahkan lagi tetes steril 8oBrix sebanyak 1/3 volume semula dan di tambah pupuk 1% demikian seterusnya sampai di peroleh volume total 50 L dan baru kemudian di pindahkan ke tangki starter (Nur.Hidayat,dkk.,2006).
Ragi tidak akan menjalankan fungsinya apabila faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhannya tidak di penuhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ragi (Suriawiria, S., 1987) antara lain :
1. Nutrisi (zat gizi)
Ragi memerlukan pertambahan nutrisi untuk berkembang biak dan pertumbuhannya seperti; Unsur C pada karbohidarat untuk mencukupi energi pertumbuhannya, Unsur N banyak terdapat pada urea dan amonia, Unsur P banyak terdapat pada pupuk pospat,NPK, TSP, Mineral seperti Mg dan Cl.
2. Kekuatan Asam (pH)
Ragi yang digunakan dalam proses fermentasi etanol memerlukan media asam, yaitu pH antara 4-5. Pengaturan pH di lakukan dengan penambahan H2SO4 dan HCl jika substratnya alkalis dan di lakukan penambahan NaOH jika substratnya dalam keadaan asam.
3. Temperatur
Suhu pertumbuhan ragi pada proses fermentasi etanol yaitu antara 25-33 oC. Apabila suhu dibawah 25oC dan diatas 33oC, ragi tidak dapat bertahan hidup.
4. Oksigen
Fermentasi etanol berlangsung secara anaerobik. Namun demikian oksigen dari udara tetap di perlukan oleh ragi selama berkembang biak (aerobik).
5. Waktu
Bila suatu sel mikroorganisme diinokulasi pada media nutrien segar, pertumbuhan yang terlihat mula-mula adalah suatu pembesaran ukuran, volume dan berat sel. Dikenal empat fase pertumbuahan selama pertumbuhan mikroorganisme, yaitu :
a. Fese lambat
Fase lambat terjadi pada awal di inokulasi di mana tidak terjadi pembelahan sel selang beberapa unit atau beberapa jam tergantung dari jenis umur sel serta lingkungannya. Waktu pada perpisahan dan penyesusian diri dengan kondisi pertumbuhan dalam lingkungan baru.
b. Fase pertumbuhan
Setelah beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru, sel-sel ini akan tumbuh dan membela diri secara eksponensial dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama. Pertumbuhan populasi mikroorganisme biasanya di batasi oleh habisnya bahan gizi yang tersedia atau penimbunan zat racun sebagai hasil aktif metabolisme.
c. Fase tetap
Populasi mikroorganisme yang dapat tumbuh secara eksponensial dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama. Pertumbuhan populasi mikroorganisme biasanya di batasi oleh habisnya bahan gizi yang tersedia atau penimbunan zat racun sebagai hasil aktif metabolisme.
d. Fese menurun
Sel-sel pada fase tetap akan mati bila tidak di pindahkan ke media segar lainnya (Buckle, K.A.,dkk, 1987).
2.3 Proses Fermentasi
2.3.1 Pengertian Fermentasi
Kata fermentasi berasal dari bahasa latin yaitu “ fervere” yang berarti merebus. Arti kata dari bahasa latin tersebut dapat di kaitkan dengan kondisi cairan bergelembung atau mendidih. Keadaan ini di sebabkan oleh adanya aktifitas ragi pada ekstrak buah-buahan atau biji-bijian. Gelembung-gelembung CO2 dihasilkan dari katabolisme anaerobik terhadap kandungan gula (Gumbira, E.S., 1989).
Fermentasi mempunyai arti yang berbeda bagi ahli biokimia dan mikro biologi industri. Arti fermentasi pada bidang biokimia di hubungkan dengan pembangkitan energi oleh katabolisme senyawa organik. Sedangkan pada bidang mikrobiologi industri, fermentasi mempunyai arti yang lebih luas yang menggambarkan setiap proses untuk menghasilkan produk dari pembiakan miroorganisme (Machfud, 1989).
Dalam suatu industri, baik itu di lakukan dengan teknik fermentasi, kimiawi maupun fisik, yang perlu di perhatikan adalah stabilitas dari komponen-komponen pendukung kegitan proses tersebut. Industri akan dapat berkembang dengan pesat bila di tinjau dari aspek teknis, social, dan financial saling mendukung. Industri fermentasi untuk menghasilkan etanol, meskipun telah di lakukan oleh negar-negara maju sejak berabad-abad yang lalu, tetapi para peneliti masih terus melakukan penelitian khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dari proses. Banyaknya etanol yang di hasilkan dapat di tentukan dengan cara analisis atau dari bacaan inventori sesudah destilasi. Tiap-tiap metode untuk analisis etanol dalam fermentasi tunggal atau kelompok mempunyai nilai tersendiri dalam suatu industri. Akan tetapi akuntan dan manajemen mengutamakan hasil, yang menunjukkan keuntungan dari produk yang terjual tiap unit bahan baku, sementara tenaga-tenaga teknik tidak harus melihat efisiensi (Nur Hidayat, dkk., 2006).
Efisiensi fermentasi merupakan indeks atau indikator kondisi fisiologi dari khamir sedangkan efisiensi pabrik merupakan standar untuk evaluasi semua proses, mulai dari bahan baku fermentasi atau melalui destilasi bila dasarnya adalah banyaknya etanol dalam tangki penyimpanan. Fermentasi khamir dalam dalam bubur biji-bijian sebagai bahan baku menghasilkan feisiensi fermentasi sebesar 98 % ditambah atau di kurangi 2 % dari jumlah gula yang di fermnetasikan dan efisiensi dari proses (atas dasar kadar pati yang di proses) akan bervariasi, tergantung dari jumlah biji-bijian yang di fermentasi dan juga di analisis patinya. Hasil etanol umunya di laporkan atas dasar banyaknya gallon tiap satuan bahan baku (bushel). Standar yang digunakan di Amerika, satu bushel adalah 56 lb (Nur Hidayat,dkk.,2006).
Perubahan arti kata fermentasi sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh para ahli. Arti kata fermentasi berubah pada saat Gay Lussac berhasil melakukan penelitian yang menunjukkan penguraian gula menjadi alkohol dan CO2. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam dalam keadaan (tanpa). Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk, akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah, dan. Akan tetapi beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti dan. dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan dalam, dan minuman beralkohol lainnya. Respirasi anaerobik dalam selama kerja yang keras (yang tidak memiliki akseptor elektron eksternal), dapat dikategorikan sebagai bentuk fermentasi (Chemiawan Tata, 2007).
Selanjutnya Lois Pasteur melakukan penelitian mengenai penyebab perubahan sifat bahan yang di fermentasi sehingga di hubungkan dengan mikroba dan akhirnya dengan enzim. Pasteur berpendapat bahwa proses penguraian gula menjadi alkohol dan CO2 di sebabkan oleh aktifitas dan sel-sel khamir yang tumbuh dan berkembang biak dalam cairan fermentasi tanpa suplai oksigen bebas dari udara (anaerob). Oleh karena itu “ia” menyebut proses fermentasi alkohol sebagai kehidupan tanpa oksigen. Lebih lanjut juga pasteur menjelaskan bahwa sel-sel khamir memperoleh energi dari hasil pemecahan moleku-molekul gula dalam keadaan tanpa udara, seperti halnya jaringan hewan atau tumbuhan yang mengoksidasi senyawa-senyawa organik dalam keadaan adanya suplai oksigen dari udara bebas atau di sebut juga aerob (Machfud, 1989).
Penjelasan pasteur tersebut di sempurnakan oleh buchner yang menunjukkan bahwa fermentasi dapat berlansung dalam larutan gula dengan menggunkan cairan yang di ekstrak dari sel-sel khamir yang sudah mati. Kemudian di ketahui bahwa cairan ini mengandung substansi aktif yang mampu memecah molekul gula dan di beri nama ferment,enzyme atau zymase. Teori yang di jelaskan aktifitas enzym mikrobial dalam fermentasi, di susun setelah penemuan energi yang di gunakan oleh sel khamir dalam keadaan tanpa udara atau di sebut juga anaerob (Gumbira, E.S., 1989).
Menurut Winarno (1984), fetrmentasi adalah salah satu reaksi oksidasi reduksi dalam sistem biologi yang menghasilkan energi, di mana sebagai donor dan akseptor elektron adalah karbohidrat dalam bentuk monosakarida dan disakarida. Senyawa tersebut akan diubah oleh enzim menjadi suatu bentuk lain misalnya alkohol yang kemudian di oksidasi menjadi asam. Terjadi fermentasi mengakibatkan perubahan sifat bahan pangan seperti timbulnya rasa dan bauh alkohol dari bahan tersebut. Secara kimiawi reaksinya adalah sebagai berikut :
E. Amilase
C12H22O12 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
(Glukosa) (Fruktosa)
E.Invertase
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
Dari uraian di atas, fermentasi berarti disimilasi anaerobik senyawa-senywa organik yang di sebabkan oleh aktifitas mikroorganisme dalam ekstrak sel tersebut. Tetapi umumnya sekarang mencakup juga aksi mikroba yang terkontrol. Dengan arti yang lebih luas fermentasi tidak hanya mencakup proses-proses disimilasi seperti pembentukkan alkohol dan asam laktat, tetapi juga asam cuka, asam sitrat, enzim, penisilin dan antibiotik serta riboflavin dan vitamin-vitamin lainnya. Karena bahan-bahan ini merupakan hasil proses mikrobial, maka disebut produk fermentasi (Gumbira,E.S., 1989).
2.3.2 Fermentasi Karbohidrat
Produk etanol dengan cara fermetasi dapat di hasilkan dari tiga macam karbohidrat, yaitu:
a. Bahan yang mengandung gula, misalnya nira.
b. Bahan-bahan yang mengandung pati, misalnya bii-bijian (jagung, beras, dan
sorgum)
c. Bahan-bahan berserat, misalnya : sulphit liquor
Karbohidrat adalah merupakan suatu senyawa yang mempunyai peranan penting dalam memproduk alkohol (etanol) secara fermentasi. Pada awalnya karbohidrat ini di hidrolisis menjadi senyawa yang paling sederhana (monosakarida) seperti glukosa yang kemudian senywa sederhana ini mengalami fermentasi menjadi alkohol yang di bantu oleh ragi sebagai mikroba.Etanol merupakan hasil antara yang mana pada reaksi selanjutnya membentuk asam asetat. Sumber karbohidrat peragian bergantung pada ketersediaanya dan pada tujuan alcohol (Fessenden, F., 1997).
Reaksi lengkap dari proses fermentasi alkohol ini adalah :
C6H12O6 + ADP + 2 Pi 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP + 2H2O
Jadi produksi etanol dengan menggunakan khamir/ragi (Sacharomyces cereviceae) adalah suatu proses anaerob, meskipun pertumbuhan sel baru memerlukan oksigen (Lehninger, A.L., 1991)
Bahan hasil pertanian yang berkadar pati tinggi, meliputi biji-bijian (gandum, jagung, beras, dll), kacang-kacangan dan umbi-umbian (kentang, ubi jalar dan ubi kayu). Karbohidrat dalam bentuk zat pati tersebut untuk pembuatan ethanol harus dihidrolisis dahulu menjadi glukosa. Pada potensi berbagai jenis tanaman yang biasa dibudi-dayakan dan dapat dijadikan bahan baku bioethanol. Berdasarkan hasil panennya terlihat, bahwa beet dan kentang merupakan tanaman pilihan terbaik untuk daerah beriklim sedang. Adapun tebu dan ubi kayu tampaknya paling potensial untuk daerah tropis. Ubi kayu bersifat lebih kokoh dan tidak memerlukan persyaratan kualitas tanah yang tinggi (Anonim., 2009).
Adapun nira yang biasa dideras dari berbagai jenis palma (Arena Pinnata,Barossus Flebellifer Cocos Nucifera and Nifa Fruticans) kandungan total sugarnya berkisar 10-20%. Apabila dibudidayakan dengan baik, akan sangat potensial dimanfaatkan untuk pembuatan ethanol, karena produktifitasnya bisa mencapai 20 ton gula per hektar per tahun (Dalibard, 1997). Pengolahannya untuk bahan baku bioethanol akan diperoleh 8,8 ton atau setara 11.000 liter Fuel Grade Ethanol perhektar per tahun (Anonim., 2009).
Fermentasi etanol sering di lakukan dalam tangki fermentasi. Fermentasi di lakukan pada kepekatan tetes 24o Brix dengan kadar gula total ± 15%. Kalau kadar gula rendah maka di tambahkan tetes baru. pH diatur menjadi 4-5. Agar terjadi fermentasi etanol maka di butuhkan kondisi anaerob sehingga sel-sel ragi dapat melakukan fermentasi yang akan mengubah tetes yang mengandung gula menjadi etanol. Pada proses fermentasi ini terjadi peningkatan panas. Agar panas yang timbul dapat di serap maka di perlukan pendingin untuk menjaga suhu yang tetap pada 30oC selama proses fermentasi yang berlangsung selama 30-40 jam. Gas CO2 yang terjadi dalam tangki fermentasi di tampung menjadi satu untuk kemudian direcovery. Alkohol yang ikut aliran gas CO2 dipisahkan dengan cara ditangkap oleh air, yaitu dengan adanya water crabber yang diletakkan di atas tangki. Pada akhir fermentasi kadar etanol berkisar anatara 8-10% volume. Hasil fermentasi ini dialirkan ke bak penampung dan kemudian dipompa ke bagian destilasi. Cairan hasil fermentasi disebut bir (Nur. Hidayat, dkk.,2006).
gula menjadi etanol merupakan salah satu paling awal yang pernah dilakukan manusia. Efek dari konsumsi etanol yang memabukkan juga telah diketahui sejak dulu. Pada zaman modern, etanol yang ditujukan untuk kegunaan industri dihasilkan dari produk sampingan pengilangan minyak bumi. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Contohnya adalah pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam kimia, etanol adalah pelarut yang penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Dalam sejarahnya etanol telah lama digunakan sebagai bahan bakar (Anonim, 2009).
Penerapan teknologi fermentasi ethanol dalam skala industri, sejak Perang Dunia II belum ada perubahan yang mendasar. Proses fermentasinya menggunakan system bacth dengan masa inkubasi berkisar 50 jam dan semata-mata mengandalkan strain khamir yang telah terpilih secara nyata berproduktivitas tinggi. Khamir mempunyai sifat selektivitas sangat tinggi untuk membentuk ethanol (metabolite lain sebagai hasil samping sangat kecil) dan sangat tahan terhadap perubahan kondisi pertumbuhan atau gangguan kontaminasi (Maiorella dkk, 1981). Konsentrasi ethanol dalam broth di akhir proses, berkisar 8 sampai 12%v.v dan selanjutnya dipekatkan (dimurnikan) dengan proses distilasi atau cara lain. Berbagai penelitian maupun pengembangan modifikasi sistem proses fermentasi dan atau penggunaan mikroba lain, telah banyak dilakukan untuk memperbaiki hasil, meningkatkan konsentrasi ethanol dalam broth dan mempersingkat waktu proses (Alico , dkk., 1982).
Bahan baku untuk pembuatan ethanol secara fermentasi berupa karbohidrat, dan hampir semua karbohidrat terbentuk dalam tanaman melalui proses photosintesa, baik sebagai gula (sakharida) yang terdiri dari satu atau dua gugus sukrosa, maupun senyawa lebih komplek sebagai zat pati dan selulosa.
Bahan sumber gula yang dapat dibuat menjadi ethanol, meliputi nira tebu, nira kelapa, nira aren, beet dan sweet sorghum, namun bahan ini paling mahal dan biasa digunakan dalam industri gula. Molases sebagai hasil samping dari industri pembuatan gula tersebut, lebih umum digunakan sebagai bahan baku industri ethanol, dari pada langsung diambil niranya. Keuntungan penggunaan nira gula dan molases dalam industri ethanol, yaitu tidak memerlukan proses pendahuluan karena bentuk senyawa karbohidratnya sudah siap diubah oleh mikrobia (Kosaric dkk, 1981).
2.4 Uraian Tentang Alkohol
2.4.1 Tinjauan Alkohol Secara Umum
Alkohol merupakan turunan hidrokarbon dengan gugus hidroksil yang berdampingan dengan suatu atom karbon jenuh (Kroschwtz, I.J., Winokur, M., 1990). Menurut Monick, A.J. (1968) Alkohol dapat diklasifikasikan berdasarkan :
a. Jumlah gugus hidroksinya (monohidrik, dihidrik, trihidrik dan polihidrik)
b. Konfigurasi molekul bagian hidrokarbon (alifatik, alisiklik, heterosiklik, aromatik, alcohol tak jenuh) dan
c. Posisi gugus hidroksi (primer, sekunder dan tersier)
Alcohol secara komersial dapat di buat dengan dua cara, yaitu secara sintetik dan secara fermentasi.
Alkohol merupakan bahan kimia yang diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sagu biasanya disebut dengan bio-ethanol. Ubi kayu, ubi jalar, dan jagung merupakan tanaman pangan yang biasa ditanam rakyat hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga jenis tanaman tersebut merupakan tanaman yang potensial untuk dipertimbangkan sebagai sumber bahan baku pembuatan bio- ethanol atau gasohol. Namun dari semua jenis tanaman tersebut, ubi kayu merupakan tanaman yang setiap hektarnya paling tinggi dapat memproduksi ethanol. Selain itu pertimbangan pemakaian ubi kayu sebagai bahan baku proses produksi bio-ethanol juga didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Pertimbangan keekonomian pengadaan bahan baku tersebut bukan saja meliputi harga produksi tanaman sebagai bahan baku, tetapi juga meliputi biaya pengelolaan tanaman, biaya produksi pengadaan bahan baku, dan biaya bahan baku untuk memproduksi setiap liter ethanol/bio-ethanol (Suti Jastoto.,2005)
Secara umum ethanol/bio-ethanol dapat digunakan sebagai bahan baku industry turunan alkohol, campuran untuk miras, bahan dasar industri farmasi, campuran bahan bakar untuk kendaraan. Mengingat pemanfaatan ethanol/bio-ethanol beraneka ragam, sehingga grade ethanol yang dimanfaatkan harus berbeda sesuai dengan penggunaannya. Untuk ethanol/bio-ethanol yang mempunyai grade 90-96,5% vol dapat digunakan pada industri, sedangkan ethanol/bio- ethanol yang mempunyai grade 96-99,5% vol dapat digunakan sebagai campuran untuk miras dan bahan dasar industri farmasi. Berlainan dengan besarnya grade ethanol/bio- ethanol yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan yang harus betul-betul kering dan anhydrous supaya tidak korosif, sehingga ethanol/bio-ethanol harus mempunyai grade sebesar 99,5-100% vol. Perbedaan besarnya grade akan berpengaruh terhadap proses konversi karbohidrat menjadi gula (glukosa) larut air. Mengacu dari penjelasan tersebut, disusunlah kajian penulisan yang berjudul “Teknologi Proses Produksi Bio-Ethanol” (Suti, Jastoto, 2005)
Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya masih mengandung gas- gas antara lain CO2 (yang ditimbulkan dari pengubahan glucose menjadi ethanol/bio-ethanol) dan aldehyde yang perlu dibersihkan. Gas CO2 pada hasil fermentasi tersebut biasanya mencapai 35 persen volume, sehingga untuk memperoleh ethanol/bio-ethanol yang berkualitas baik, ethanol/bio-ethanol tersebut harus dibersihkan dari gas tersebut. Proses pembersihan (washing) CO2 dilakukan dengan menyaring ethanol/bio-ethanol yang terikat oleh CO2, sehingga dapat diperoleh ethanol/bio-ethanol yang bersih dari gas CO2). Kadar ethanol/bio-ethanol yang dihasilkan dari proses fermentasi, biasanya hanya mencapai 8 sampai 10 persen saja, sehingga untuk memperoleh ethanol yang berkadar alkohol 95 persen diperlukan proses lainnya, yaitu proses destilasi. Proses destilasi dilaksanakan melalui dua tingkat, yaitu tingkat pertama dengan beer column dan tingkat kedua dengan rectifying colum. Definisi kadar alkohol atau ethanol/bio-ethanol dalam % (persen) volume adalah “volume ethanol pada temperatur 15oC yang terkandung dalam 100 satuan volume larutan ethanol pada temperatur tertentu (pengukuran).“ Berdasarkan BKS Alkohol Spiritus, standar temperatur pengukuran adalah 27,5o C dan kadarnya 95,5% pada temperatur 27,5 oC atau 96,2% pada temperatur 15 oC. Pada umumnya hasil fermentasi adalah bio-ethanol atau alkohol yang mempunyai kemurnian sekitar 30 – 40% dan belum dapat dikategorikan sebagai fuel based ethanol. Agar dapat mencapai kemurnian diatas 95% , maka lakohol hasil fermentasi harus melalui proses destilasi (Wittcoff, 1980).
2.4.2 Sifat dan Kegunaan Etanol
Etanol adalah salah satu alkohol primer yang memiliki sifat-sifat antara lain ; merupakan cairan tak berwarna seperti air, mudah larut dalam air, berbau khas, volatile, massa mlekul relative = 46 gram/mol, massa jenis = 0,7905 gram/mL (20 oC), viskositas 0,0122 poise (20 oC), titik didih 78 oC (1 atm)
Etanol tidak hanya berguna pada industri-industri kimia, tetapi juga berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti :
a. Sebagai bahan baku pembuatan spiritus (etanol di tambah dengan metanol lalu
diberi zat warna).
b. Sebagai bahan pelarut misalnya dalam pembuatan obat.
c. Sebagai bahan pembuatan minuman keras.
d. Sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik dan parfum.
e. Dapat mendenaturasi protein dan megendapkannya. Prinsip ini di pakai dalam
penggunaan etanol sebagi antiseptic dan untuk hal ini di gunakan etanol 70 %
(Streiwieser, A., and Co.,1985).
Etanol merupakan salah satu produk fermentasi yang banyak digunakan sebagai pelarut dan zat antara di industri farmasi dan kimia. Produksi etanol secara fermentasi umumnya menggunakan ragi dari spesies Saccharomyces dan Schizosaccharomyces. Fermentasi etanol oleh kedua spesies ini menghasilkan perolehan etanol yang tinggi. Pada saat ini fermentasi etanol di Indonesia umumnya menggunakan ragi Saccharomyces. Ethanol untuk kebutuhan industri dapat dibuat secara fermentasi dari karbohidrat, yang produknya disebut sebagai bioethanol; atau hasil reaksi kimia dengan cara hidrasi ethylene, memakai katalis asam pospat. Ethanol dari hidrasi gas ethylene yang merupakan hasil samping pemurnian minyak bumi, dikenal sebagai ethanol sintetis (Alico, D.H.,1982).
Ethanol untuk kebutuhan industri dapat dibuat secara fermentasi dari karbohidrat, yang produknya disebut sebagai bioethanol; atau hasil reaksi kimia dengan cara hidrasi ethylene, memakai katalis asam pospat. Ethanol dari hidrasi gas ethylene yang merupakan hasil samping pemurnian minyak bumi, dikenal sebagai ethanol sintetis. Setelah Perang II, eksplorasi minyak bumi secara besar-besaran memungkinkan pembuatan ethanol sintetis lebih murah dan menggantikan proses produksi ethanol secara fermentasi. Namun sejak kenaikan harga yang disertai ketidak-pastian penyediaannya, telah memacu berbagai negara Eropa, US, Brazil, untuk mengembangkan kembali teknologi pembuatan ethanol secara fermentasi, terutama bertumpu pada sumber daya yang dapat terbarukan. Pembuatan ethanol secara sintetis tidak dibahas lagi, mengingat salah satu tujuan pengembangan produk alkohol di sini, adalah sebagai bahan bakar cair pengganti minyak bumi Penerapan teknologi fermentasi ethanol dalam skala industri, sejak Perang Dunia II belum ada perubahan yang mendasar. Proses fermentasinya menggunakan system bacth dengan masa inkubasi berkisar 50 jam dan semata-mata mengandalkan strainkhamir yang telah terpilih secara nyata berproduktivitas tinggi (Wittcoff, 1980).
Etanol adalah cairan tak berwarna yang mudah menguap dengan aroma yang khas. Ia terbakar tanpa asap dengan lidah api berwarna biru yang kadang-kadang tidak dapat terlihat pada cahaya biasa. Sifat-sifat fisika etanol utamanya dipengaruhi oleh keberadaan gugus dan pendeknya rantai karbon etanol. Gugus dapat berpartisipasi ke dalam ikatan hidrogen, sehingga membuatnya cair dan lebih sulit
menguap dari pada senyawa organik lainnya dengan massa molekul yang sama. Etanol adalah pelarut yang serbaguna, larut dalam air dan pelarut organik lainnya, meliputi, dan. Ia juga larut dalam hidrokarbon alifatik yang ringan, seperti dan, dan juga larut dalam senyawa klorida alifatik seperti dan. Campuran etanol-air memiliki volume yang lebih kecil daripada jumlah kedua cairan tersebut secara terpisah. Campuran etanal dan air dengan volume yang sama akan menghasilkan campuran yang volumenya hanya 1,92 kali jumlah volume awal. Pencampuran etanol dan air bersifat dengan energi sekitar 777 J/mol dibebaskan pada 298 K. Campuran etanol dan air akan membentuk dengan perbandingkan kira-kira 89% mol etanol dan 11% mol air. Perbandingan ini juga dapat dinyatakan sebagai 96% volume etanol dan 4% volume air pada tekanan normal dan T = 351 K. Komposisi azeotropik ini sangat tergantung pada suhu dan tekanan. Ia akan menghilang pada temperatur di bawah 303 K (Hennell, H., 1987).
2.4.3 Tahapan Produksi Etanol
Secara umum, pembuatan etanol secara fermetasi terbagi dalam beberapa tahap, antara lain :
1. Penyiapan bahan baku
Penyiapan bahan baku di lakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses fermentasi, antara lain dengan melakukan pemisahan terhadap bahan yang sejenis, pencucian dan penghalusan jika perlu.
2. Hidrolisa
Dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pati menjadi gula monosakarida agar dapat dengan mudah di konversi menjadi alcohol (etanol).
3. Pembuatan Starter
Tahap ini di maksud untuk memperbanyak sel-sel ragi sebelum digunakan untuk fermentasi. Ragi ini di kembangbiakkan dalam suatu substrat yang telah dihidrolisis.
4. Destilasi
Substrat hasil fermentasi masih mengandung konsentrasi etanol yang rendah. Untuk meningkatkan konsentrasinya maka perlu di lakukan destilasi. Destilasi adalah suatu proses pemisahan campuran homogen yang komponen-komponennya mempunyai perbedaan titik didih nyata. Destilasi merupakan cara yang mudah untuk dioperasikan dan juga merupakan cara pemisahan yang paling efisien. Maksud tahap ini adalah untuk memisahkan etanol dengan air (Gumbira, E.S,. 1997).
BAB III
METODE PENULISAN KAJIAN
3.1 Metode Pengumpulan Bahan Kajian
Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penulisaan deskriptif yang di lakukan dengan penelusuran, pengumpulan dan telaa pustaka yang relavan dengan masalah yang di kaji. Bahan kajian tersebut berasal dari referensi primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan. Referensi di peroleh dari berbagai media cetak ( Jurnal,dan Buku-buku) dan media elektronik (internet)
3.2 Prosedur Penulisan
Prosedur Penulisan yang di lakukan dalam Karya tulis ini adalah :
a. Identifikasi Masalah
b. Kerangka penulisan untuk mengetahui data-data dan informasih yang di butuhkan
sebagai bahan analisa kajian
c. Penelusuran pustaka dan pengumpulan bahan kajian
d. Analisis deskriptif terhadap bahan-bahan yang terkumpul
e. Penulisan karya tulis.
3.3 Sistematika Penulisan
Sitematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut :
1. Bagian Awal.
a. Halaman Judul
b. Lembar Pengesahan
c. Kata Pengantar
d. Daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar
e. Ringkasan
2. Bagian Inti
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Kajian Pustaka
1.3 Manfaat Kajian Pustaka
1.4 Rumusan Masalah
Bab II. Tinjauan Pustaka
2.1 Uraian tentang pisang
2.1.1 Klasifikasi Pisang
2.1.2 Komposisi kulit pisang
2.2 Mikroorganisme dan faktor-fakto yang mempengaruhi pertumbuhan
2.3 Fermentasi
2.3.1 Pengertian fermentasi
2.3.2 Fermentsi karbohidrat
2.4 Uraian tentang alkohol
2.4.1 Tinjauan alkohol secara umum
2.4.2 Sifat dan kegunaan alkohol
2.4.3 Tahapan produksi etanol
Bab III.Metode penulisan
3.1 Metode pengumpulan data
3.2 Prosedur penulisan
3.3 Sistematika penulisan
Bab IV Hasil dan pembahasan
Bab V. Penutu
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
Daftara Pustaka
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam proses fermentasi etanol dari beberapa limbah kulit pisang menggunakan Khamir Saccromyces cereviseae pada suhu pertumbuhannya 30 oC dan pH 4,1- 4,7 dalam massa peragian 2- 8 hari. Ragi yang di gunakan dalam proses fermentasi etanol memerlukan media asam yaitu pH antara 4,1 dan 4,7 pengaturan pH di lakukan penambahan H2SO4 dan HCl jika substratnya alkalis dan di lakukan penambahan NaOH jika subtratnya dalam keadaan asam. Untuk fermentasi alkohol, ragi memerlukan media suasana asam, yaitu antara pH 4,1– 4,3. Kondisi optimum, pembuatan etanol secara fermentasidari kulit pisang meliputi pH, waktu dan suhu :
4. 1. pH Optimum
pH pada produksi etanol secara fermentasi dari beberapa limbah kulit pisang menggunakan khamir Saccromyces cereviseae dapat di lihat pada tabel 1. Di bawah ini menurut percobaan Gowlanto,G.A dan Tallasa., (1998). Bentuk data pada tabel 1. Dapat di ketahui bahwa kadar etanol hasil fermentasi dari berbagai kulit pisang pada pH yang berbeda dengan suhu 30 oC dan waktu fermentasi selama 2-8 hari.
Tabel 1: pH optimum konsentrasi etanol pada fermentasi beberapa jenis pisang
Jenis pisang pH Konsentrasi (%)
Pisang raja 4,1 17,87
Pisang ambon 4,3 17,36
Pisang kepok 4,5 12,063
Pisang cavendish 4,7 6,06
Standar 99,8
Berdasarkan tabel hasil berdasarkan pengamatan pengamatan kadar etanol hasil fermentasi pada berbagai kulit pisang yang menggunakan khamir Saccromyces cereviseae pada berbagai pH dengan suhu 30 oC dengan waktu fermentasi yang tetap yaitu 8 hari, menunjukkan bahwa pH fermentasi sangat perpengaruh terhadap jumah produk etanol yang dihasilkan, di peroleh kadar alcohol hasil pengamatan yang tertinggi adalah pada pH 4,1 dengan kadar alcohol 17,83 %. Terlihat bahwa pH 4,1 dan pH 4,3 kadar etanol yang di hasilkan tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun pada pH 4,5 mengalami penurunan kadar etanol yang cukup drastis yaitu 12,063 % pada pH 4,5 hingga 6,06 % pada pH 4,7.
Gambar 1. Hubungan antara pH optimum dengan konsentrasi produk etanol yang di
hasilkan dari masing-masing pisang.
Hal ini disebabkan karena pada pH sekitar 4,1 dan pH 4,3 merupakan kondisi efektif bekerjan khamir Saccromyces cereviseae sedangkan pada keadaan yang lebih netral,khamir tersebut tidak bekerja efektif. Fakta tersebut di tunjang oleh beberapa penelitian sebelumnya dengan menggunakan substrat yang berbeda seperti pada dua penelitian berikut ini. Dalam penelitian Gowlanto,G.A (1998) yang mencapai pH optimum pada pH 4,2 dengan konsentrasi etanol 20 %, dimana kondisi fermentasi 30 oC selama waktu 8 hari dengan substrat nira nipah. Sedangkan pada penenlitian Tallasa (1998) yang menggunakan substrat sisa makanan, waktu fermentasi 8 hari dan suhu 30 oC yang di peroleh pH optimum pada pH 4,3 dengan konsentrasi etanol 25,12 %.
Pengaruh pH merupakan satu diantara beberapa factor penting yang mampu mempengaruhi proses pada fermentasi etanol. pH optimum untuk proses fermentasiadalah antara 4,1 – 4,7. Pada dibawah pH 4 atau lebih dari 4 proses fermentasi akan berkurang kecepatan kerja mikrobannya. Dalam penelitian Gowlanto, G.A dan Tallasa (1998) kondisi pH pada proses fermentasi yaitu 4,1 ; 4,3 ; 4,5 , dan 4,7, kisaran pH di antara ini telah memperoleh hasil konsentrasi etanol yang di tampilkan pada gambar 1. Konsentrasi etanol paling tinggi di hasilkan pada proses fermentasi dengan pH 4,1 yaitu sebesar 17.87 %.
pH optimum media kompleks dengan konsentrasi alkohol 17,87 pada pH yang berbeda (4,1; 4,3; 4,5 dan 4,7) digunakan dalam fermentasi untuk mengetahui pengaruh pH terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, konsentrasi etanol maksimum 17,87 % diperoleh pada pH 4,1.
Gumbira (1987) mengemukakan bahwa rentang pH optimum untuk produksi etanol dengan kadar yang relatif stabil oleh S. cerevisiae yang teramobilisasi adalah pada pH 4,1 – 4,7. Dalam penelitian ini terjadi penurunan etanol yang cukup signifikan pada pH di atas dan di bawah 4. Pada pH 4,1; 4,3 ; 4,5 dan 4,7 hanya dihasilkan etanol masing-masing 17,87 ; 17, 36 ; 12,063 dan 6,06 %. Nilai pH awal media fermentasi sangat mempengaruhi kadar etanol yang dihasilkan.
4. 2. Waktu Fermentasi
Waktu produksi etanol secara fermentsi dari limbah kulit pisang raja,ambon, kepok, dan Cavendish menggunakan khamir Saccromyces cereviseae dapat di lihat pada tebel 2. Menurut percobaan Gowlanton, G. A dan Tallasa (1998)
Tabel 2. Kadar etanol hasil fermentasi dari berbagai kulit pisang pada berbagai waktu
yang berbeda dengan suhu 30 oC dan waktu fermentasi selama 2-8 hari
adalah :
Jenis pisang Waktu fermentasi (hari) Konsentrasi (%)
Pisang raja 2 17,87
Pisang ambon 4 17,36
Pisang kepok 6 12,063
Pisang cavendish 8 6,06
Standar 99,8
Penentuan waktu fermentasi di lakukan pada pH optimum yang telah di peroleh, dalam hal ini pH 4,1dan pada suhu 30 oC. Dari data hasil penelitian yang di peroleh sesuai gambar 2 menunjukkan bahwa waktu fermentasi yang sangat berpengaruh terhadap produk etanol yang di hasilkan, di mana pada waktu fermentasi 2 hari produk etanol yang di hasilkan cukup banyak. Konsentrasi etanol mengalami penurunan sedikit demi sedikit hingga mencapai produk etanol paling paling sedikit dengan konsentrasi 17,36 % pada waktu fermentasi 4 hari (kondisi optimum). Selanjutnya waktu fermentasi di atas 4 hari, etanol yang di hasilkan mulai menurun. Hal ini membuktikan bahwa waktu fermentasi lebih dari 4 hari pertumbuhan mikroorganisme sebagai biokatalis sangat lemah (fase lambat) sehingga laju reaksinya pun lambat. Hal ini mengakibatkan etanol yang di hasilkan relatif sedikit.
Gambar 2. Hubungan antara waktu fermentasi dengan konsentrasi produk etanol
Kondisi optimum dicapai pada waktu fermentasi 2 hari dengan konsentrasi yang di peroleh 17,87 %, di mana mikroorganisme sebagai kabiokatalis aktif sempurna yang menyebabkan laju reaksi cepat sehingga produk etanol yang di hasilkan banyak. Selanjutnya waktu fermentasi 4 hari sampai 8 hari produk etanol yang di hasilkan menurun. Hal ini disebabkan karena keaktifan mikroorganisme mulai menurun. Pada waktu fermentasi diatas 8 hari merupakan akhir dari keaktifan mikroorganisme sehingga produk etanol yang dihasilkan menurun drastis. Penenlitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk variasi waktu fermentasi oleh Umar, S., (2001) dengan menggunakan bahan makanan sisa substratnya pada pH fermentasi 4,5 dan suhu 30 oC diperoleh hasil yang sama dimana waktu fermentasi optimum bekerjanya khamir Saccromyces cereviseae adalah pada waktu fermentasi hari ke 2 dengan konsentrasi etanol 17,87 % . Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan pH ferrmentasi dan waktu fermentasi optiumum untuk jenis pisang yang berbeda.
Waktu pertumbuhan suatu sel mikroorganisme diinokulasi pada media nutrien segar, pertumbuhan yang terlihat mula-mula adalah suatu pembesaran ukuran, volume dan berat sel. Dikenal empat fase pertumbuahan selama pertumbuhan mikroorganisme, yaitu :
e. Fese lambat
Fase lambat terjadi pada awal di inokulasi di mana tidak terjadi pembelahan sel selang beberapa unit atau beberapa jam tergantung dari jenis umur sel serta lingkungannya. Waktu pada perpisahan dan penyesusian diri dengan kondisi pertumbuhan dalam lingkungan baru.
f. Fase pertumbuhan
Setelah beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru, sel-sel ini akan tumbuh dan membela diri secara eksponensial dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama. Pertumbuhan populasi mikroorganisme biasanya di batasi oleh habisnya bahan gizi yang tersedia atau penimbunan zat racun sebagai hasil aktif metabolisme.
g. Fase tetap
Populasi mikroorganisme yang dapat tumbuh secara eksponensial dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama. Pertumbuhan populasi mikroorganisme biasanya di batasi oleh habisnya bahan gizi yang tersedia atau penimbunan zat racun sebagai hasil aktif metabolisme.
h. Fese menurun
Sel-sel pada fase tetap akan mati bila tidak di pindahkan ke media segar lainnya
4. 3. Suhu Optimum
Suhu optimum pada fermentasi dari beberapa jenis limbah kulit pisang menggunakan khamir Saccromyces cereviseae sama yaitu pada suhu 30 oC dapat di lihat pada tabel di bawah ini menurut percobaan Gowlanton, G.A dan Tallasa (1998).
Tabel 3. Kadar etanol hasil fermentasi dari beberapa kulit pisang pada suhu yang
sama 30 oC dan waktu fermentasi selama 2 – 8 hari adalah :
Jenis pisang Suhu optimum Konsentrasi (%)
Pisang raja 30 oC 17,87
Pisang ambon 30 oC 17,36
Pisang kepok 30 oC 12,063
Pisang cavendish 30 oC 6,06
Standar 99,8
Dalam penenlitian Gowlanton,G.A dan Tallasa (1998) suhu optimum untuk fermentasi etanol menggunakan khamir Saccromyces cereviseae adalah 30 oC. Karena pada suhu 30 oC aktivitas miroba bekerja lancar, pada kondisi mikroba pada suhu tersebut dapat di peroleh konsentras 17.87 %,dari pisang raja di mana mikroorganisme sebagai biokatalis aktif sempurna yang menyebabkan laju reaksi cepat sehingga produk etanol yang di hasilkan banyak. Suhu pertumbuhan ragi pada proses fermentasi etanol yaitu antara 30 oC. Apabila suhu dibawah 30 oC dan diatas 30 oC, ragi tidak dapat bertahan hidup. Temperatur optimum untuk mengembangbiakan khamir adalah 30 oC pada waktu fermentasi, terjadi kenaikan panas, karena ekstrem. Untuk mencegah agar suhu fermentasi tidak naik, perlu pengaturan supaya suhu dipertahankan tetap 30 oC.
Gambar 3. Hubungan antara waktu fermentasi terhadap suhu optimum konsentrai
etanol yang di hasilkan
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.3 Kesimpulan
Berdasarkan tabel dan grafik pada penulisan kajian dapat di tarik kesimpulan bahwa :
1. Etanol yang diperoleh secara fermentasi dari beberapa jenis kulit pisang menggunkan khamir Saccromyces cereviseae tergantung pada kandungan karbohidrat masing-masing pisang tersebut.
2. Konsentrasi etanol paling tinggi yang didapatkan dari fermentasi kulit pisang raja,menggunakan khamir Saccromyces cereviseae yaitu 17, 87 % pada pH 4.1 dan suhu optimum 30 oC selama waktu fermentasi 2 hari
5.4 Saran
Perlu di lakukan penulisan lebih lanjut tentang kadar etanol untuk bahan yang lain khususnya limbah yang banyak mengandung polisakarida.
DAFTAR PUSTAKA
1. Anonim, 2009., Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Untuk Pembuatan Etanol.http//www.
Wikipedia_blokspot,. Di akses tanggal 27 oktober 2009 pukul 20.00
2. Alico,D.H., 1982, Alcohol Fuels,Production and Potential, West View Press
(Boulder) Colorado.
3. Bucle, K.A., Edwars RA, Fleet, GH dan Cotton, M., 1987, Ilmu Pangan, Universitas
Indonesia, Jakarta.
4. Chemiawan Tata., 2007. Membangun Industri Bioetanol Nasional Sebagai Pasokan Energi
Berkelanjutan Dalam Menghadapi Krisis Energi Global. Tata Chemiawan’s weblog.
5. Dwidjoseputro, D., 1989, Dasar-Dasar Mikrobiologi, Penerbit Dambatan,Bandung.
6. Fessenden, F., 1997, Kimia Organik, Jilid I, Edisi Ketiga Penerbit Erlangga. Hal 267
7. Gumbira, E.S., 1987, Bioindustri Penerangan Teknologi Fermentasi, Mediyatama, Sarana
Perkasa, Jakarta.Hal 3-5 & 264-272.
8. Gunnter, R.J. Bobbitt, J.M. dan Sewaring, 1991, Pengantar Kromatografi Diterjemahkan
Oleh Kosasih Padmawinata, Penerbi Institut Teknologi Bandung.
9. Hennell, H. 1987, On The Mutual Action Of Sulfuric Acid And Alcohol, And On The Nature
Of The Process By Which Ether Is Formed. Philosophical Transactions 118 (365-71)
10. Kosaric, N., Z. Duvnja, dan G.G. Stewart, 1981, Fuel Ethanol from Biomass: Production,
Economics and Energy , Biotech. Bioeng.
11. Kroschwitz, I.J., Winokur, M., 1990, Chemistry, General, Organic and Biological, Second
Edition, MC. Graw Hill Publishing Company,New York Hal 417-457.
12. Lehninger, A.L., 1991, Terjemahan Maggy Theniwijaya, Dasar-Dasar Biokimia,
Jilid 2, Penerbit Erlangga. Hal 103-105.
13. Machfud, 1989, Alcoholic Fermentation Of Mollasses,Edit Industria Fermentation
Vol. I Chemical Publishing Co. New York.
14. Nurhidayat.,Masdiana C. Padaga., Sri Suhartini.,2006, Mikrobiologi Industri,
Penerbit ANDI Yogyakarta
15. Rahman, A., 1994 Teknologi Fermentasi Industrial, Editor Surya Satyanegara,
Cetakan ke- 2,Arcan, Jakarta
16. `Supriyadi, A., Satuhu, Suryani.,1996, Pisang budidaya, pengolahan, dan prospek
pasar,Cetakan 6, Penebar Swadaya,Jakarta.
17. Suriawiria, S., 1986, Pengantar Mikrobiologi Umum, Penerbit Angkasa Bandung
18. Suyanti A.,Supriyadi.,2008, Pengolahan dan Prospek Pemasaran Pisang, Penebar Swadaya
Informasi Dunia Pertanian
19. Suti Jastoto., 2005, Pembuatan Etanol Secara Fermentasi dari Sisa Makanan, Skripsi
(Tidak di Publikasikan), Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilm
Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar.
20. Steriwieser A., and Co.,1985, Introduction to Organik Chemistry, Fourt Edition,
Macmilla Publishing Company, New York. Hal 207
21. Witcoff H.A., dan B.G.Reuber., 1980, Industrial Organic Chemicals In Perspective, Part
One,Raw Matrials and Manufacture.New York.
Senin, 31 Mei 2010
Minggu, 04 April 2010
PEMANFAATAN RUMPUT LAUT (Euchema cottonii) SEBAGAI ADSORBEN ION TIMBAL(II) DALAM PERAIRAN
PEMANFAATAN RUMPUT LAUT (Euchema cottonii) SEBAGAI ADSORBEN ION TIMBAL(II) DALAM PERAIRAN
YUSUF PEKEI
H31106205
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Permasalahan lingkungan hidup merupakan hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup (Bappedal, 1997). Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena adanya aktifitas yang dilakukan oleh manusia maupun karena pengaruh alam. Salah satu akibat samping dari kegiatan pembangunan diberbagai sektor dan daerah adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup (Tandjung, 1991).
Sejalan dengan perkembangan sektor industri pada beberapa daerah telah terjadi berbagai kasus pencemaran terhadap sumber-sumber air, lebih jauh dari itu bahan pencemar air yang seringkali menjadi masalah terhadap masyarakat dan lingkungan adalah terdapatnya limbah bahan berbahaya dan beracun (Brahmana dan Moelyo, 2003).
Kontaminasi logam berat di lingkungan merupakan masalah besar dunia saat ini. Persoalan spesifikasi logam berat di lingkungan terutama karena keberadaannya di alam dan akumulasinya sampai pada rantai makanan dan keberadaannya di alam, serta meningkatnya logam berat yang menyebabkan keracunan terhadap tanah, udara dan air. Proses industri dan urbanisasi memegang peranan penting terhadap peningkatan kontaminan tersebut (Suhendrayatna, 2001).
Secara alami logam mengalami siklus perputaran dari kerak bumi ke lapisan tanah, ke dalam makhluk hidup, ke dalam kolom air, mengendap dan akhirnya kembali lagi ke dalam kerak bumi, tetapi kandungan alamiah logam berubah-ubah tergantung pada kadar pencemaran yang dihasilkan manusia maupun karena erosi alami. Pencemaran akibat aktivitas manusia lebih banyak berpengaruh dibandingkan pencemaran secara alami. Timbal merupakan salah satu logam berat yang banyak terkandung dalam air buangan industri terutama industri elektroplating atau metalurgi dan industri yang menggunakan logam sebagai bahan baku proses. Keberadaan logam Pb di dalam air buangan sangat berpotensi mencemari lingkungan. (Prihatiningsih, 2001).
Mengingat resiko yang dapat ditimbulkan oleh logam berat, pemanfaatan sistem adsorpsi untuk pengambilan logam-logam berat dari perairan telah banyak dilakukan. Beberapa spesies alga telah ditemukan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mengadsorpsi ion-ion logam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk sel mati (biomassa). Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa gugus fungsi yang terdapat dalam alga mampu melakukan pengikatan dengan ion logam seperti yang telah dilakukan oleh Davis, dkk., (2000) menggunakan Sargassum dan Figueira dkk., (2000) yang menggunakan biomassa Durvillaea, Laminaria, Ecklonia sebagai biosorben logam berat.
Berkaitan dengan uraian di atas, akan dilakukan penelitian tentang pemanfaatan rumput laut Euchema Cottonii untuk penyerapan ion Pb2+. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas pencemaran logam berat di perairan.
1.2. Rumusan masalah
1. Berapa besar kapasitas penyerapan ion Pb2+ oleh rumput laut (Euchema Contonii) berdasarkan variasi waktu dan konsentrasi?
2. Apakah interaksi ion Pb2+ dengan rumput laut (Euchema Contonii) dapat diterapkan sebagai solusi alternatif bagi masalah pencemaran logam berat di lingkungan perairan?
1.3 Maksud dan tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan E.cottonii menyerap ion logam terutama ion Pb2+.
1.3.2 Tujuan
1. Menentukan kapasitas penyerapan ion Pb2+ oleh rumput laut (Euchema Cottonii) berdasrkan variasi waktu dan konsentrasi.
2. Menentukan kapasitas penyerapan rumput laut (Euchema Contonii)? terhadap ion Pb2+.
1.4. Manfaat
Manfaat penelitian ini antara lain berupa informasi tentang parameter interaksi Euchema Cottonii terhadap ion Pb2+ sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengolah lingkungan perairan yang terkontaminasi oleh logam berat.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Keadaan Perairan
Indonesia telah dikenal luas sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu 80.791,42 Km. Di dalam lautan terdapat bermacam-macam mahluk hidup baik berupa tumbuhan air maupun hewan air. Salah satu mahluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut adalah alga (Putra, 2006). Lautan merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia, kita dapat bayangkan jika lautan kita tercemar/rusak sehingga sebagian dari biomasa itu tercemar. Sementara 60% populasi manusia bumi ini tinggal di 60 km dari sebuah pantai yang sangat bergantung pada hasil laut (Sudrajad, 2006).
Secara normal, laut memiliki daya asimilasi untuk memproses dan mendaur ulang bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam badan air. Akan tetapi dengan semakin tingginya konsentrasi akumulasi bahan pencemar ke dalam perairan laut akan mengakibatkan daya asimilatif laut sebagai gudang sampah menjadi menurun dan menimbulkan masalah lingkungan. Dampak pencemaran ini memberi pengaruh dalam kehidupan manusia, organisme lain serta lingkungan sekitarnya. Untuk itu secara dini sumber pencemar dan bahan-bahan pencemar perlu dikendalikan agar kelak tidak merusak lingkungan laut. Logam Pb dan Hg yang merupakan jenis bahan pencemar di laut, selain dapat menurunkan kualitas dan produktivitas perairan laut, juga dapat menimbulkan keracunan, karena unsur Hg dan Pb merupakan unsur logam berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia apabila terakumulasi pada organisme perairan yang dikonsumsi manusia (Siahainenia, 2001). Logam yang ada pada perairan suatu saat akan turun dan mengendap pada dasar perairan, membentuk sedimentasi, hal ini akan menyebabkan organisme yang mencari makan di dasar perairan (udang, rajungan, dan kerang) akan memiliki peluang yang besar untuk terpapar logam berat yang telah terikat di dasar perairan dan membentuk sedimen (Rahman, 2006).
Pencemaran laut oleh logam berat bukan lagi merupakan suatu masalah baru yang mengancam kesejahteraan hidup manusia. Karena laut telah lama dipandang sebagai tempat akhir yang cocok untuk pembuangan limbah yang dihasilkan oleh manusia, dengan anggapan bahwa volume lautan di dunia ini sangat luas yang mempunyai kemampuan tidak terbatas untuk menyerap segala sesuatu yang dibuang ke dalamnya baik sengaja maupun yang tidak disengaja (Nybakken, 1988).
Sastrawijaya (1991) menyatakan bahwa pencemaran perairan merupakan masalah lingkungan hidup yang perlu dipantau sumber dan dampaknya terhadap ekosistem. Dalam memantau pencemaran air digunakan kombinasi komponen fisika, kimia dan biologi. Penggunaan salah satu komponen saja sering tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penggunaan komponen fisika dan kimia saja hanya akan memberikan gambaran kualitas lingkungan sesaat dan cenderung memberikan hasil dengan penafsiran dan kisaran yang luas, oleh sebab itu penggunaan komponen biologi juga sangat diperlukan karena fungsinya yang dapat mengantisipasi perubahan pada lingkungan kualitas perairan.
2.2 Uraian Umum Logam Berat
Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar yang sangat berbahaya bagi organisme karena dapat memberikan pengaruh letal dan subletal. Pengaruh sub letal tersebut dapat berupa gangguan terhadap morfologi atau histologi, fisiologi (pertumbuhan, perkembangan, kemampuan untuk berenang, bernafas, sirkulasi), biokimia (keadaan kimia darah, kegiatan enzim dan endokrinologi), perilaku atau neurofisiologi dan perkembangbiakan atau reproduksi (Suryani dan Liong, 2003).
Logam-logam tertentu sangat berbahaya bila ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam lingkungan (dalam air, tanah dan udara), karena logam tersebut mempunyai sifat yang merusak jaringan tubuh mahluk hidup. Pencemaran lingkungan oleh logam-logam berbahaya (Cd, Pb, Hg), dapat terjadi jika orang atau pabrik yang menggunakan logam tersebut untuk proses produksinya tidak memperhatikan keselamatan lingkungan. Logam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu logam esensial dan logam non esensial. Logam esensial adalah logam yang sangat membantu dalam proses fisiologi mahluk hidup dengan jalan membantu kerja enzim atau pembentukan organ dari makhluk yang bersangkutan. Sedangkan logam non esensial adalah logam yang peranannya dalam tubuh tidak diketahui, kandungannya dalam jaringan hewan sangat kecil, dan apabila kandungannya tinggi akan dapat merusak organ-organ tubuh makhluk yang bersangkutan (Darmono, 1995).
Menurut Miettinen (1977) dalam Marganof (2003) logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih besar dari 5 gr/cm3, terletak di sudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari perioda 4 sampai 7. Sebagian besar logam berat seperti Pb, Cd, Cr dan Hg berpengaruh besar terhadap lingkungan karena toksisitasnya (Husain dan Muchtar, 2005). Menurut Darmono (1995) daftar urutan toksisitas logam paling tinggi ke paling rendah sebagai berikut Hg2+ > Cd2+ >Ag2+ > Ni2+ > Pb2+ > As2+ > Cr2+ Sn2+ > Zn2+.
2.3 Timbal
Timbal atau yang kita kenal sehari -hari dengan timah hitam dan dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan kata plumbum (Pb). Logam ini termasuk ke dalam kelompok logam-logam golongan IVA pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan bobot atom (BA) 207,2 adalah suatu logam berat berwarna kelabu kebiruan dan lunak dengan titik leleh 327 oC dan titik didih 1.620 oC. Pada suhu 550-600 oC, Pb menguap dan membentuk oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah timbal(II) (Palar, 1994).
Timbal merupakan salah satu logam berat yang banyak terkandung dalam air buangan industri terutama industri elektroplating atau metalurgi dan industri yang menggunakan logam sebagai bahan baku proses. Keberadaan logam Pb di dalam air buangan sangat berpotensi mencemari lingkungan. (Prihatiningsih, 2001). Logam timbal berasal dari buangan industri metalurgi, yang bersifat racun dalam bentuk Pb-arsenat. Kadang-kadang terdapat dalam bentuk kompleks dengan zat organik seperti hexaetil timbal, dan tetra alkil lead (TAL) (Iqbal dan Qodir, 1990).
Logam Pb terdapat di perairan baik secara alamiah ataupun sebagai dampak dari aktifitas manusia. Logam ini masuk ke perairan melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Di samping itu, proses korosifikasi dari batuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur sumber Pb yang akan masuk ke dalam perairan (Palar, 2004). Diperkirakan 95% Pb dalam sedimen nonorganik dan organik dibawa oleh air sungai menuju samudera (Herman, 2006).
2.3.1 Absorpsi dan Dampak Pb bagi Tubuh
Timbal dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui absorpsi timbal pada sayuran, asap hasil pembakaran TEL yang diabsorpsi kulit dan dihirup, serta air minum yang terkontaminasi timbal organik atau ion timbal. Fisik timbal sangat mirip dengan kalsium, sehingga timbal dapat masuk ke peredaran darah dan sel saraf menggantikan kalsium (Martaningtyas, 2004).
Menurut Darmono (1995), timbal mungkin berpengaruh negatif pada semua orang yaitu dengan mengganggu enzim oksidase sebagai akibatnya menghambat sistem metabolisme sel, salah satu diantaranya adalah menghambat sintesis Hb dalam sumsum tulang. Timbal menghambat enzim sulfuhidril untuk mengikat delat-aminolevulinik asid (ALA) menjadi porpobilinogen, serta protoforfirin-9 menjadi Hb. Hal ini menyebabkan anemia dan adanya basofilik stipling dari eritrosit yang merupakan ciri khas dari keracunan Pb. Basofilik terjadi karena retensi dari DNA ribosoma dalam sitoplasma eritrosit sehingga mengganggu sistem protein.
Adanya timbal dalam peredaran darah dan dalam otak juga mengakibatkan berbagai gangguan fungsi jaringan dan metabolisme. Gangguan mulai dari sintesis haemoglobin darah, gangguan pada ginjal, sistem reproduksi, penyakit akut atau kronik sistem syaraf, serta gangguan fungsi paru-paru (Martaningtyas, 2004).
Timbal dan senyawanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan, sedangkan absorbsi melalui kulit sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Timbal yang diabsorsi diangkut oleh darah ke organ-organ tubuh sebanyak 95% Pb dalam darah diikat oleh eritrosit. Ekskresi Pb melalui urine sebanyak 75–80%, melalui feses 15% dan lainnya melalui empedu, keringat, rambut, dan kuku (Palar,1994).
Bahaya yang ditimbulkan oleh Pb tergantung oleh ukuran partikelnya. Partikel yang lebih kecil dari 10 µg dapat tertahan di paru-paru, sedangkan partikel yang lebih besar mengendap di saluran nafas bagian atas (Ardyanto, 2005). Dampak lebih jauh dari keracunan Pb adalah dapat menyebabkan hipertensi dan salah satu faktor penyebab penyakit hati. Ketika unsur ini mengikat kuat sejumlah molekul asam amino, haemoglobin, enzim, RNA, dan DNA maka akan mengganggu saluran metabolik dalam tubuh. Keracunan Pb dapat juga mengakibatkan gangguan sintesis darah, hipertensi, hiperaktivitas, dan kerusakan otak (Herman, 2006).
2.3 Rumput laut
Perairan Indonesia berpotensi besar untuk budidaya rumput laut dengan tehnik pengolahan yang mudah, penanganan yang sederhana dengan modal kecil sehingga di Indonesia berkembang industri pengolahan rumput laut. Salah satu di antaranya adalah PT. Bantimurung Indah Kab. Maros Sulawesi selatan yang mengolah rumput laut Jenis Euchema contonii dan Euchema spinosum (Yustin, dkk., 2005). Rumput laut atau yang biasa disebut dengan seaweed merupakan tanaman makroalga yang hidup di laut yang tidak memiliki akar, batang dan daun sejati dan pada umumnya hidup di dasar perairan. Rumput laut juga sering disebut sebagai alga atau ganggang pada daerah-daerah tertentu di Indonesia (Juneidi, 2004).
Menurut Afrianto dan Liviawati, (1993) fungsi dari akar, batang dan daun yang tidak dimiliki oleh rumput laut tersebut digantikan dengan thallus. Karena tidak memiliki akar, batang dan daun seperti umumnya pada tanaman, maka rumput laut digolongkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah (Thallophyta). Bagian–bagian rumput laut secara umum terdiri dari holdfast yaitu bagian dasar dari rumput laut yang berfungsi untuk menempel pada substrat dan thallus yaitu bentuk-bentuk pertumbuhan rumput laut yang menyerupai percabangan. Rumput laut memperoleh atau menyerap makanannya melalui sel-sel yang terdapat pada thallusnya. Nutrisi terbawa oleh arus air yang menerpa rumput laut akan diserap sehingga rumput laut bisa tumbuh dan berkembangbiak. Perkembangbiakan rumput laut melalui dua cara yaitu generatif dan vegetatif.
Gambar 1. Morfologi rumput laut (Afrianto dan Liviawati, 1993)
Ditinjau secara biologi, rumput laut merupakan kelompok tumbuhan yang berklorofil yang terdiri dari satu atau banyak sel dan berbentuk koloni. Di dalam alga terkandung bahan-bahan organik seperti polisakarida, hormon, vitamin, mineral dan juga senyawa bioaktif. Berbagai jenis alga seperti Griffithsia, Ulva, Enteromorpna, Gracilaria, Euchema, dan Kappaphycus telah dikenal luas sebagai sumber makanan seperti salad rumput laut atau sumber potensial karagenan yang dibutuhkan oleh industri gel. Begitupun dengan Sargassum, Chlorela/Nannochloropsis yang telah dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat (Putra, 2006).
Selain yang telah disebutkan di atas di dalam rumput laut juga terdapat mineral esensial (besi, iodin, aluminum, mangan, kalsium, nitrogen dapat larut, phosphor, sulfur, chlor. silikon, rubidium, strontium, barium, titanium, kobalt, boron, tembaga, kalium, dan unsur-unsur lainnya yang dapat dilacak), protein, tepung, gula dan vitamin A, D, C, D. Persentase kandungan zat-zat tersebut bervariasi tergantung dari jenisnya (Anonim, 2006). Pemanfaatan rumput laut yang demikian besarnya disebabkan dalam rumput laut terkandung beragam zat kimia dan bahan organik lain seperti vitamin (Hidayat, 1994).
Menurut Juneidi (2004), Alga merah merupakan kelompok alga yang jenis-jenisnya memiliki berbagai bentuk dan variasi warna salah satu indikasi dari alga merah adalah terjadi perubahan warna dari warna aslinya menjadi ungu atau merah apabila alga tersebut terkena panas atau sinar matahari secara langsung. Alga merah merupakan golongan alga yang mengandung karagenan dan agar yang bermanfaat untuk industri kosmetik dan makanan. Salah satu contoh rumput laut jenis alga merah yang bernilai ekonomis dan terdapat di perairan laut Indonesia adalah Eucheuma cottoni.
Ciri-ciri umum alga merah adalah :
- Bentuk thalli ada yang silindris (Gelidium latifolium), pipih (Gracillaria folifera) dan lembaran (Dictyopteris sp.)
- Warna thalli bervariasi ada yang merah (Dictyopteris sp.), pirang (Eucheuma spinosum), coklat (Acanthophora muscoides) dan hijau (Gracillaria gigas).
- Sistem percabangan thalli ada yang sederhana, kompleks,dan juga ada yang berselang – seling.
- Mengandung pigmen fotosintetik berupa karotin, xantofil, fikobilin, dan r-fikoeritrin penyebab warna merah dan klorofil a dan d.
Menurut Samsuari, (2006) beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut adalah fakor lingkungan yang meliputi:
1. Suhu
Pengaruh suhu terhadap sifat fisiologi organisme perairan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fotosintesis disamping cahaya dan konsentrasi fosfat. Perbedaan suhu terjadi karena adanya perbedaan energi matahari yang diterima oleh perairan. Suhu akan naik dengan meningkatnya energi matahari yang masuk ke dalam perairan. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan fotosintesis sampai pada radiasi tertentu. Kecepatan fotosintesis akan konstan dan produksi maksimum tidak tergantung pada energi matahari lagi sampai pada reaksi enzimatis. Fotosintesis maksimal bagi Eucheuma adalah pada suhu 21 – 31,2 oC, sedangkan pada suhu di atas 32 oC aktivitas fotosintesis terhambat.
2. Salinitas
Salinitas perairan berperan penting bagi organisme laut terutama dalam mengatur tekanan osmosis yang ada dalam tubuh organisme dengan cairan lingkungannya. Salinitas di perairan dipengaruhi oleh penguapan dan jumlah curah hujan. Salinitas tinggi terjadi jika curah hujan yang turun di suatu perairan kurang yang menyebabkan penguapan tinggi. Sebaliknya, jika curah hujan tinggi maka penguapan berkurang dan salinitas menjadi rendah.
3. Kecepatan arus
Pergerakan air mempengaruhi bobot, bentuk thallus dan produksi bahan-bahan hidrokoloid Eucheuma. Gerakan air (arus) yang baik untuk pertumbuhan rumput laut antara 20 – 40 cm/detik.
4. pH
Hampir seluruh alga mempunyai kisaran daya penyesuaian terhadap pH antara 6,8 – 9,6.
2.3.1 Eucheuma cottonii
Menurut Doty (1985) dalam Samsuari (2006), Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut merah (Rhodophyceae) dan berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. Maka jenis ini secara taksonomi disebut Kappaphycus alvarezii Nama daerah ‘cottonii’ umumnya lebih dikenal dan biasa dipakai dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional. Ciri fisik Eucheuma cottoni memiliki ciri-ciri yaitu Thallus silindris, permukaan licin, melekat pada sustrat dengan alat perekat berupa cakram (Juneidi, 2004), keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. (Aslan, 1998).
Lokasi budidaya rumput laut jenis ini di Indonesia antara lain Lombok, Sumba, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Kepulauan Seribu, dan Perairan Pelabuhan Ratu (Atmadja, 1996 dalam Samsuari 2006).
Klasifikasi Eucheuma cottonii menurut Doty (1985) dalam Samsuari (2006) adalah sebagai berikut :
Klasifikasi
Divisio/Phylum : Rhadophyta
Class : Rhodophyceae
Sub class : Florideophycidae
Ordo : Gigartinales
Famili : Soliericiae
Genus : Eucheuma
Spesies : Eucheuma cottonni (Kapaphycus alvarezii)
Gambar 2. Eucheuma cottoni (amsuari, 2006)
2.3.2 Rumput Laut sebagai Adsorben Logam Berat
Pemanfaatan sistem adsorpsi untuk pengambilan logam-logam berat dari perairan telah banyak dilakukan. Beberapa spesies alga telah ditemukan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mengadsorpsi ion-ion logam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk sel mati (biomassa). Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa gugus fungsi yang terdapat dalam alga mampu melakukan pengikatan dengan ion logam. Gugus fungsi tersebut terutama adalah gugus karboksil, hidroksil, sulfudril, amino, iomodazol, sulfat, dan sulfonat yang terdapat didalam dinding sel dalam sitoplasma (Putra, 2006). Rumput laut menawarkan keuntungan untuk biosorpsi karena memiliki struktur yang makroskopis sehingga dapat digunakan sebagai biosorben (Regine, dkk., 2000).
Dari berbagai penelitian di ketahui bahwa berbagai spesies alga terutama dari golongan alga hijau (Chlorophyta), alga coklat (Phaeophyta), dan alga merah (Rhodophyta) baik dalam keadaan hidup (sel hidup) maupun dalam bentuk sel mati (biomassa) dan biomassa terimmobilisasi telah mendapat perhatian untuk mengadsorpsi ion logam. Alga dalam keadaan hidup dimanfaatkan sebagai bioindikator tingkat pencemaran logam berat di lingkungan aquatik (perairan) sedangkan alga dalam bentuk biomassa dan biomassa terimmobilisasi dimanfaatkan sebagai biosorben (material biologi penyerap logam berat) dalam pengolahan air limbah (Putra, dkk., 2006).
Menurut Phillips (1980) makroalga merupakan indikator yang paling tepat dan efisien untuk pencemaran logam berat, karena mikroorganisme ini dapat mengakumulasi pencemar, terdapat dalam jumlah banyak, dan korelasi antara kandungan bahan pencemar dalam air dan dalam tubuh organisme dapat ditunjukkan.
Menurut Putra, dkk. (2006) keuntungan pemanfaatan alga sebagai bioindikator dan biosorben adalah:
(1) Alga mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam mengadsorpsi logam berat karena di dalam alga terdapat gugus fungsi yang dapat melakukan pengikatan dengan ion logam.
(2) Bahan bakunya mudah didapat dan tersedia dalam jumlah banyak
(3) Biaya operasional yang rendah
(4) Tidak perlu nutrisi tambahan
Gambar 3. Struktur sel dari Alga (Regine, dkk., 2000)
Mekanisme pengikatan ion-ion logam oleh alga terjadi melalui beberapa cara seperti adsorpsi melalui pertukaran ion, kompleksasi, serta entrapmen (Harris dan remelow 1990 dalam Raya 2001).
Ladeiro, dkk., (2006) menggunakan makroalga Cystoseira baccata sebagai biosorben untuk Cd(II) dan Pb(II) dengan studi kinetika dan kesetimbangan menunjukkan bahwa Cystoseira baccata mampu melakukan pengambilan logam dengan cepat, study kinetika dan kesetimbangan menunjukkan logam yang diserap sekitar 0.9 mmol/g ( 101mg/g untuk cadmium(II) dan 186 mg/g untuk dan lead(II) ) pada pH 4.5 Hashim dan Chu (2004) membandingkan besarnya kapasitas penyerapan logam cadmium oleh tiga jenis biomassa alga yaitu: alga coklat, alga merah, dan hijau. Hasil yang dioperoleh menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan maksimum pada pH 5 adalah alga merah < alga hijau < alga coklat, dengan kapasitas penyerapan sebesar 0,74 mmol/gram Sargassum baccularia (alga coklat) dan 0,48 mmol/gram Chaetomorphalinum (alga hijau) dan 0,23 mmol/gram Glcsilaria changii (alga merah). Dengan menggunakan model adsorpsi langmuir, Antunes, dkk., (2003) melaporkan bahwa biomassa Sargassum sp. potensial untuk menyerap ion Cu2+ dengan kapasitas penyerapan sebesar 1,48 mmol/g.
2.4 Adsorpsi
Adsorpsi adalah peristiwa terkonsentrasinya suatu zat pada permukaan zat lain. Zat yang menyerap disebut adsorben sedangkan zat yang diserap seperti molekul, atom atau ion disebut adsorbat (Laidler, 1982 dalam Tondok, 2001). Menurut Petrucci-Suminar (1987) terjadinya proses adsorpsi melibatkan gaya-gaya intermolekul seperti, gaya elektrostatik, gaya London serta antraksi ion-ion yang terdapat pada adsorben maupun adsorbat, sehingga proses adsorpsi akan melibatkan perubahan energi. Jika adsorpsi dipandang sebagai suatu reaksi kesetimbangan, maka pada keadaan setimbang ∆G = 0, sehingga energi adsorpsi dapat dirumuskan sebagai berikut :
-∆Go = -RT ln K (1)
Alberty dan Silbey (1992), menyatakan bahwa adsorpsi secara umum dapat didefinisikan sebagai akumulasi sejumlah molekul (senyawa, ion maupun atom) yang terjadi pada batas antara dua fasa. Adsorpsi dapat terjadi antara dua fasa seperti antara fasa cair-padat, fasa gas-padat, dan fasa gas-cair.
Berdasarkan besarnya interaksi antara adsorben dan adsorbat, maka adsorpsi dapat dibedakan menjadi adsorpsi kimiawi dan adsorpsi fisikawi. Adsorpsi kimia melibatkan pembentukan ikatan kimia, meskipun pada umumnya tidak ada perbedaan yang sangat jelas antara kedua jenis adsorpsi ini kecuali perubahan entalphinya dimana perubahan entalphi kimia lebih besar dari pada adsorpsi fisika yaitu berkisar 40 sampai 200 kj/mol. Adsorpsi kimia bergantung pada energi aktivasi (energi minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya adsorpsi). Besarnya energi adsorpsi menyebabkan adsorbat sangat sukar untuk dilepaskan dari permukaan adsorben, sedangkan banyaknya molekul yang teradsorpsi merupakan fungsi tekanan, konsentrasi dan suhu. Adsorpsi fisikawi merupakan proses yang sangat reversible, dengan waktu kesetimbangan yang tercapai segera setelah adsorbat bersentuhan dengan adsorben, di samping itu terjadi adsorpsi berlangsung dalam beberapa lapisan monomolekuler yang membutuhkan kondisi tekanan dan temperatur tertentu (Alberty dan Silbey 1992).
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut jenis Euchema cottonii, larutan induk Pb 1000 ppm, PbO2, aquades, dan air laut steril.
3.2 Alat
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat gelas yang umum digunakan di laboratorium, aerator, baskom (wadah untuk menumbuhkan rumput laut), tali, lampu neon, serta Spektropotometer Serapan Atom (SSA).
3.3 Waktu dan tempat pengambilan sampel
Pengambilan sampel dilakukan pada bulan maret 2008 di desa Gusungnge, Kel. Jalanjang, Kec.Gantarang, Kab.Bulukumba. Sampel ditumbuhkan di laboratorium kimia anorganik selama 45 hari.
3.4 Waktu dan Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2008 di laboratorium Kimia anorganik Universitas hasanuddin, Makassar
3.5 Prosedur Kerja
3.5.1 Pembuatan larutan induk Pb2+ 1000 ppm
Larutan induk Pb2+ 1000 ppm dibuat dengan cara melarutkan 1,1544 gram PbO2 dalam labu ukur 1000 mL.
3.5.2 Pembuatan Larutan Baku Timbal 100 Ppm
Larutan induk 1000 ppm dipipet 50 mL ke dalam labu ukur 500 mL, kemudian diimpitkan hingga tanda batas.
3.5.3 Penyiapan Media Pertumbuhan
3.5.3.1 Penyiapan Media Pertumbuhan Terkontaminasi Pb2+ 15 ppm
Larutan induk Pb2+ dipipet sebanyak 75 mL dan dimasukkan dalam wadah pertumbuhan yang berisi 5 L air laut.
3.5.3.2 Penyiapan Media Pertumbuhan Yang Terkontaminasi Pb2+ 5, 10,15 dan 20 ppm
Larutan induk Pb2+ 1000 ppm dipipet sebanyak 25 mL, 50 mL, 75 mL, dan 100 mL dan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi 5 L air laut.
3.5.4 Penentuan Kadar Timbal yang diserap oleh E.Cottoni berdasarkan waktu kontak
Euchema cottonii dicuci lalu dibersihkan dengan tissue, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram dalam berat basah. Euchema cottonii yang sudah ditimbang tersebut ditumbuhkan dalam wadah (baskom) yang telah diisi dengan 5 L air laut dan Pb2+ 15 ppm selama 45 hari. Selanjutnya diamati dan dicacat perubahan yang terjadi. Setiap hari ke-8 air laut yang digunakan menumbuhkan E.Cottonii dianalisis dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom.
3.5.1 Penyerapan Euchema cottonii terhadap Pb2+ berdasarkan variasi Konsentrasi
Euchema cottonii dicuci lalu dibersihkan dengan tissue, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram. Euchema cottonii yang sudah ditimbang tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam wadah (baskom) yang telah diisi dengan 5 L air laut dan Pb2+ 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm,20 ppm dan 25 ppm, lalu ditumbuhkan selama 45 hari. Diamati perubahan yang terjadi sampai pada hari ke 45. Air laut yang digunakan untuk menumbuhkan Euchema cottonii tersebut dianalisis menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom. Untuk menentukan kadar Pb2+ diserap oleh E.Cottoni dapat digunakan persamaan sebagai berikut:
Konsentrasi teradsorpsi = konsentrasi awal – konsentrasi akhir
Cadsorpsi = (Cawal – Cakhir)
Banyaknya ion-ion logam yang teradsorpsi (mg) per gram adsorben ditentukan menggunakan persamaan:
Keterangan:
Qe = jumlah ion logam yang teradsorpsi (mg/g)
C0 = konsentrasi ion logam sebelum adsorpsi
Ce = konsentrasi ion logam setelah adsorpsi
V = volume larutan ion logam (L)
Wa = jumlah adsorben, (g)
DAFTAR PUSTAKA
Afrianto, E. dan Liviawati, E., 1993, Budidaya Rumput Laut dan Cara Pengolahannya, Penerbit Bhratara, Jakarta.
Anonim, 2006 Menanggulangi Pencemaran Logam Berat (online), (http://www.ychi.org - ychi.org. diakses 4 Januari, 2008, pukul 09:35 Wita).
Anonim, 2006, Pesona rumput laut sebagai sumber devisa, (online) (http//www.dkp.go.id/content.php?c=3197, diakses 3 Februari 2008, pukul 20.15 wita).
Alberty, R.A. dan Silbey, R.J., 1992, Physical Chemistry, John Wiley & Sons, Inc, Canada.
Antunes, W.M., Luna, A.s., Henriques, C.A., dan Costa, A.C.A., 2003, An evaluation of copper biosorption by a brown seaweed under optimized conditions, Electronic J. of Biotechnology ISSN: 0717-3458.
Ardyanto D., 2005, Deteksi Pencemaran Timah Hitam (Pb) Dalam Darah Masyarakat Yang Terpajan Timbal (Plumbum), Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2 (1), 67 – 7.
Aslan, M., 1998, Budidaya Rumput Laut, Yogyakarta, Kanisius.
Bappedal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1997, Badan Pengendali Dampak Lingkungan, Jakarta.
Brahmana, S.S., dan Moelyo, M., 2003, Penelitian Bioremediasi Sumber Air Tercemar Bahan Berbahaya Dan Beracun, JLP. 17 (52), 83.
Darmono, 1995, Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup, UI-Press, Jakarta.
Davis, T. A., Volesky, B. dan Vieira, R. H. S. F., 2000, Sargassum Seaweed As Biosorbent For Heavy Metals, Wat. Res. Vol. 34 (17), 4270 – 4278.
Figueira, M. M. Volesky, B., Ciminelli, V. S. T. , dan Roddick, F. A., 2000, Biosorption Of Metals In Brown Seaweed Biomass, Wat. Res. 34 (1) 196 - 204
Herman, D.Z., 2006, Tinjauan Terhadap Tailing Mengandung Unsur Pencemar Arsen (As), Merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd) dari Sisa Pengolahan Bijih Logam, Jurnal Geologi Indonesia, 1 (1) 31-36.
Hidayat, A., 1994, Budidaya Rumput Laut, Usaha Nasimal, Surabaya.
Husain, D.R. dan Muchtar, I.H., 2005, Bakteri Pengompleks Logam Pb dan Cd Dari Limbah Cair PT. Kawasan Industri Makassar, Marina Chemica Acta, 7 (1), 25-28.
Hashim dan Chu, 2004, Biosorption of cadmium by brown, green, and red seaweeds, Chemical Engineering Journal, 97(2006) 249–255
Iqbal, H.Z. dan Qodir, M.A., 1990, AAS determination of Lead and Cadmium in Leaves Polluted by Vehicles Exhoust (Interface) Juornal Environmental Analytic Chemistry, 38 (4), 533 – 538.
Juneidi, W., 2004, Rumput Laut Jenis dan Morfologisnya, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Jakarta.
Lodeiro, P., Barriada, J.L., Herrero, R., dan Sastre de Vicente, M.E., 2005, The marine macroalga Cystoseira baccata as biosorbent for cadmium(II) and lead(II) removal: Kinetic and equilibrium studies, Environmental Pollution, 1 (142), 264-273.
Marganof, 2003, Potensi Limbah Udang Sebagai Penyerap Logam Berat (Timbal, Kadmium, dan tembaga) di Perairan, Makalah Pribadi Pengantar Ke Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor.
Martaningtyas, D., 2004, Bahaya Cemaran Logam Berat, (online) (http://www.pikiran-akyat.com/cetak/0704/29/cakrawala/lainnya08.htm, diakses 25 Desember 2007 pukul 11.00 Wita).
Nybakken, J.W., 1988, Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi, Gramedia, Jakarta.
Palar. H., 1994, Pencemaran dan Toksikologi logam berat, Rineka Cipta, Jakarta.
Phillips, D.J.H., 1980. Proposal for Monitoring Studies on Metals and Organochlorines. Dalam "South Chines Fisharies Development and Coordinating Programme". Manila: FAO.
Prihatiningsih, B., 2001, Studi Kinetika Penyisihan Logam Timbal (Pb) Pada Reaktor Biologi Anaerob Dengan Sistem Batch, (Online), (http://digilib.unikom.ac.id/go.php?id=jbptitbpp-gdl-s2-2001-bekti-1105-timbal, diakses pada tanggal 5 Januari 2008 pukul 11.30 Wita)
Putra, Buhani, dan Suharso, 2006, Alga sebagai Bioindikator dan Biosorben Logam Berat,(online) (http://www.chem-is-try.org/?sect=fokus&ext=29, diakses 20 desember 2007 pukul 09.00 Wita)
Putra S. E., 2006, Alga Laut sebagai Biotarget Industri, (online), (http://www.energi.lipi.go.id) diakses 20 desember 2007 pukul 09.20 Wita).
Petrucci-Suminar, 1987, Kimia Dasar, Prinsip dan Terapan Modern, edisi ke 4, Erlangga, Jakarta.
Rahman, A., 2006, Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Beberapa Jenis Krustasea Di Pantai Batakan dan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Bioscientiae, 3 (2), 93-101.
Regine, Vieira, dan Volesky B., 2000, Biosorption: a solution to pollution?, Internatl Microbiol, Canada.
Raya I., 2001, adsorpsi ion logam Tembaga(II) dan Cadmium(II) oleh Chaetoceros calcitrans hasil immobilisasi, FMIPA UNHAS, Makassar.
Sastrawijaya, A. T., 1991, Pencemaran Lingkungan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Samsuari, 2006, Karakterisasi karaginan Eucheuma cottonii pada berbagai umur panen, konsentrasi KOH dan lama ekstraksi. http://www.damandiri.or.id/file/samsuaripbbab3.pdfhttp://www.damandiri.or.id/file/samsuaripbbab3.pdf, diakses 28 januari 2008 .
Siahainenia, L., 2001, Pencemaran Laut Dampak dan Penanggulangannya, Makalah Falsafah Sains, Program Pascasarjana IPB, Bogor, (online), (http:www.hayati-ipb.com/users/rudyct/indiv2001/lauras.htm, diakses 9 Maret 2007, pukul 10.15 Wita).
Suhendrayatna, 2001, Bioremoval Logam Berat dengan Menggunakan Mikroorganisme: Suatu Kajian Kepustakaan, (online), http://www.istecs.org/publication/Japan/010211-Suhendrayatna.PDF, diakses 14 April 2007, 10.45 Wita).
Suryani, E. dan Liong, S., 2003, Distribusi Kuantitatif Logam Berat Pb, Cd dan Cu dalam sedimen di Sekitar Perairan laut Dangkal Pulau Sumbawa, Marina Chemica Acta, 5 (2), 2-8.
Sudrajad, A., 2006, Tumpahan Minyak di Laut dan Beberapa Catatan Terhadap Kasus di Indonesia, Inovasi, 6 (18), 1.
Tandjung, S.D., 1991, Konservasi Sumber Daya Alam, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tondok, L., 2001, Pemanfaatan limbah kulit kacang (Arachis hypogeae L.) sebagai adsorben ion tembaga(II) dalam air, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Kimia FMIPA UNHAS, Makassar
Yustin, D., Angelia, D., Hala, Y. dan Taba. P., 2005, Analisis Potensi Limbah Cair Hasil Pengolahan Rumput Laut Sebagai Pupuk Buatan, Marina Chemica Acta 7 (1), 2-8.
.
.
Lampiran 1. Bagan kerja penentuan kapasitas penyerapan E. Cottoni terhadap ion Pb2+ berdasarkan waktu kontak dan variasi konsentrasi.
YUSUF PEKEI
H31106205
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Permasalahan lingkungan hidup merupakan hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup (Bappedal, 1997). Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena adanya aktifitas yang dilakukan oleh manusia maupun karena pengaruh alam. Salah satu akibat samping dari kegiatan pembangunan diberbagai sektor dan daerah adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup (Tandjung, 1991).
Sejalan dengan perkembangan sektor industri pada beberapa daerah telah terjadi berbagai kasus pencemaran terhadap sumber-sumber air, lebih jauh dari itu bahan pencemar air yang seringkali menjadi masalah terhadap masyarakat dan lingkungan adalah terdapatnya limbah bahan berbahaya dan beracun (Brahmana dan Moelyo, 2003).
Kontaminasi logam berat di lingkungan merupakan masalah besar dunia saat ini. Persoalan spesifikasi logam berat di lingkungan terutama karena keberadaannya di alam dan akumulasinya sampai pada rantai makanan dan keberadaannya di alam, serta meningkatnya logam berat yang menyebabkan keracunan terhadap tanah, udara dan air. Proses industri dan urbanisasi memegang peranan penting terhadap peningkatan kontaminan tersebut (Suhendrayatna, 2001).
Secara alami logam mengalami siklus perputaran dari kerak bumi ke lapisan tanah, ke dalam makhluk hidup, ke dalam kolom air, mengendap dan akhirnya kembali lagi ke dalam kerak bumi, tetapi kandungan alamiah logam berubah-ubah tergantung pada kadar pencemaran yang dihasilkan manusia maupun karena erosi alami. Pencemaran akibat aktivitas manusia lebih banyak berpengaruh dibandingkan pencemaran secara alami. Timbal merupakan salah satu logam berat yang banyak terkandung dalam air buangan industri terutama industri elektroplating atau metalurgi dan industri yang menggunakan logam sebagai bahan baku proses. Keberadaan logam Pb di dalam air buangan sangat berpotensi mencemari lingkungan. (Prihatiningsih, 2001).
Mengingat resiko yang dapat ditimbulkan oleh logam berat, pemanfaatan sistem adsorpsi untuk pengambilan logam-logam berat dari perairan telah banyak dilakukan. Beberapa spesies alga telah ditemukan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mengadsorpsi ion-ion logam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk sel mati (biomassa). Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa gugus fungsi yang terdapat dalam alga mampu melakukan pengikatan dengan ion logam seperti yang telah dilakukan oleh Davis, dkk., (2000) menggunakan Sargassum dan Figueira dkk., (2000) yang menggunakan biomassa Durvillaea, Laminaria, Ecklonia sebagai biosorben logam berat.
Berkaitan dengan uraian di atas, akan dilakukan penelitian tentang pemanfaatan rumput laut Euchema Cottonii untuk penyerapan ion Pb2+. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas pencemaran logam berat di perairan.
1.2. Rumusan masalah
1. Berapa besar kapasitas penyerapan ion Pb2+ oleh rumput laut (Euchema Contonii) berdasarkan variasi waktu dan konsentrasi?
2. Apakah interaksi ion Pb2+ dengan rumput laut (Euchema Contonii) dapat diterapkan sebagai solusi alternatif bagi masalah pencemaran logam berat di lingkungan perairan?
1.3 Maksud dan tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan E.cottonii menyerap ion logam terutama ion Pb2+.
1.3.2 Tujuan
1. Menentukan kapasitas penyerapan ion Pb2+ oleh rumput laut (Euchema Cottonii) berdasrkan variasi waktu dan konsentrasi.
2. Menentukan kapasitas penyerapan rumput laut (Euchema Contonii)? terhadap ion Pb2+.
1.4. Manfaat
Manfaat penelitian ini antara lain berupa informasi tentang parameter interaksi Euchema Cottonii terhadap ion Pb2+ sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengolah lingkungan perairan yang terkontaminasi oleh logam berat.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Keadaan Perairan
Indonesia telah dikenal luas sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu 80.791,42 Km. Di dalam lautan terdapat bermacam-macam mahluk hidup baik berupa tumbuhan air maupun hewan air. Salah satu mahluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut adalah alga (Putra, 2006). Lautan merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia, kita dapat bayangkan jika lautan kita tercemar/rusak sehingga sebagian dari biomasa itu tercemar. Sementara 60% populasi manusia bumi ini tinggal di 60 km dari sebuah pantai yang sangat bergantung pada hasil laut (Sudrajad, 2006).
Secara normal, laut memiliki daya asimilasi untuk memproses dan mendaur ulang bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam badan air. Akan tetapi dengan semakin tingginya konsentrasi akumulasi bahan pencemar ke dalam perairan laut akan mengakibatkan daya asimilatif laut sebagai gudang sampah menjadi menurun dan menimbulkan masalah lingkungan. Dampak pencemaran ini memberi pengaruh dalam kehidupan manusia, organisme lain serta lingkungan sekitarnya. Untuk itu secara dini sumber pencemar dan bahan-bahan pencemar perlu dikendalikan agar kelak tidak merusak lingkungan laut. Logam Pb dan Hg yang merupakan jenis bahan pencemar di laut, selain dapat menurunkan kualitas dan produktivitas perairan laut, juga dapat menimbulkan keracunan, karena unsur Hg dan Pb merupakan unsur logam berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia apabila terakumulasi pada organisme perairan yang dikonsumsi manusia (Siahainenia, 2001). Logam yang ada pada perairan suatu saat akan turun dan mengendap pada dasar perairan, membentuk sedimentasi, hal ini akan menyebabkan organisme yang mencari makan di dasar perairan (udang, rajungan, dan kerang) akan memiliki peluang yang besar untuk terpapar logam berat yang telah terikat di dasar perairan dan membentuk sedimen (Rahman, 2006).
Pencemaran laut oleh logam berat bukan lagi merupakan suatu masalah baru yang mengancam kesejahteraan hidup manusia. Karena laut telah lama dipandang sebagai tempat akhir yang cocok untuk pembuangan limbah yang dihasilkan oleh manusia, dengan anggapan bahwa volume lautan di dunia ini sangat luas yang mempunyai kemampuan tidak terbatas untuk menyerap segala sesuatu yang dibuang ke dalamnya baik sengaja maupun yang tidak disengaja (Nybakken, 1988).
Sastrawijaya (1991) menyatakan bahwa pencemaran perairan merupakan masalah lingkungan hidup yang perlu dipantau sumber dan dampaknya terhadap ekosistem. Dalam memantau pencemaran air digunakan kombinasi komponen fisika, kimia dan biologi. Penggunaan salah satu komponen saja sering tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penggunaan komponen fisika dan kimia saja hanya akan memberikan gambaran kualitas lingkungan sesaat dan cenderung memberikan hasil dengan penafsiran dan kisaran yang luas, oleh sebab itu penggunaan komponen biologi juga sangat diperlukan karena fungsinya yang dapat mengantisipasi perubahan pada lingkungan kualitas perairan.
2.2 Uraian Umum Logam Berat
Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar yang sangat berbahaya bagi organisme karena dapat memberikan pengaruh letal dan subletal. Pengaruh sub letal tersebut dapat berupa gangguan terhadap morfologi atau histologi, fisiologi (pertumbuhan, perkembangan, kemampuan untuk berenang, bernafas, sirkulasi), biokimia (keadaan kimia darah, kegiatan enzim dan endokrinologi), perilaku atau neurofisiologi dan perkembangbiakan atau reproduksi (Suryani dan Liong, 2003).
Logam-logam tertentu sangat berbahaya bila ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam lingkungan (dalam air, tanah dan udara), karena logam tersebut mempunyai sifat yang merusak jaringan tubuh mahluk hidup. Pencemaran lingkungan oleh logam-logam berbahaya (Cd, Pb, Hg), dapat terjadi jika orang atau pabrik yang menggunakan logam tersebut untuk proses produksinya tidak memperhatikan keselamatan lingkungan. Logam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu logam esensial dan logam non esensial. Logam esensial adalah logam yang sangat membantu dalam proses fisiologi mahluk hidup dengan jalan membantu kerja enzim atau pembentukan organ dari makhluk yang bersangkutan. Sedangkan logam non esensial adalah logam yang peranannya dalam tubuh tidak diketahui, kandungannya dalam jaringan hewan sangat kecil, dan apabila kandungannya tinggi akan dapat merusak organ-organ tubuh makhluk yang bersangkutan (Darmono, 1995).
Menurut Miettinen (1977) dalam Marganof (2003) logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih besar dari 5 gr/cm3, terletak di sudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari perioda 4 sampai 7. Sebagian besar logam berat seperti Pb, Cd, Cr dan Hg berpengaruh besar terhadap lingkungan karena toksisitasnya (Husain dan Muchtar, 2005). Menurut Darmono (1995) daftar urutan toksisitas logam paling tinggi ke paling rendah sebagai berikut Hg2+ > Cd2+ >Ag2+ > Ni2+ > Pb2+ > As2+ > Cr2+ Sn2+ > Zn2+.
2.3 Timbal
Timbal atau yang kita kenal sehari -hari dengan timah hitam dan dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan kata plumbum (Pb). Logam ini termasuk ke dalam kelompok logam-logam golongan IVA pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan bobot atom (BA) 207,2 adalah suatu logam berat berwarna kelabu kebiruan dan lunak dengan titik leleh 327 oC dan titik didih 1.620 oC. Pada suhu 550-600 oC, Pb menguap dan membentuk oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah timbal(II) (Palar, 1994).
Timbal merupakan salah satu logam berat yang banyak terkandung dalam air buangan industri terutama industri elektroplating atau metalurgi dan industri yang menggunakan logam sebagai bahan baku proses. Keberadaan logam Pb di dalam air buangan sangat berpotensi mencemari lingkungan. (Prihatiningsih, 2001). Logam timbal berasal dari buangan industri metalurgi, yang bersifat racun dalam bentuk Pb-arsenat. Kadang-kadang terdapat dalam bentuk kompleks dengan zat organik seperti hexaetil timbal, dan tetra alkil lead (TAL) (Iqbal dan Qodir, 1990).
Logam Pb terdapat di perairan baik secara alamiah ataupun sebagai dampak dari aktifitas manusia. Logam ini masuk ke perairan melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Di samping itu, proses korosifikasi dari batuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur sumber Pb yang akan masuk ke dalam perairan (Palar, 2004). Diperkirakan 95% Pb dalam sedimen nonorganik dan organik dibawa oleh air sungai menuju samudera (Herman, 2006).
2.3.1 Absorpsi dan Dampak Pb bagi Tubuh
Timbal dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui absorpsi timbal pada sayuran, asap hasil pembakaran TEL yang diabsorpsi kulit dan dihirup, serta air minum yang terkontaminasi timbal organik atau ion timbal. Fisik timbal sangat mirip dengan kalsium, sehingga timbal dapat masuk ke peredaran darah dan sel saraf menggantikan kalsium (Martaningtyas, 2004).
Menurut Darmono (1995), timbal mungkin berpengaruh negatif pada semua orang yaitu dengan mengganggu enzim oksidase sebagai akibatnya menghambat sistem metabolisme sel, salah satu diantaranya adalah menghambat sintesis Hb dalam sumsum tulang. Timbal menghambat enzim sulfuhidril untuk mengikat delat-aminolevulinik asid (ALA) menjadi porpobilinogen, serta protoforfirin-9 menjadi Hb. Hal ini menyebabkan anemia dan adanya basofilik stipling dari eritrosit yang merupakan ciri khas dari keracunan Pb. Basofilik terjadi karena retensi dari DNA ribosoma dalam sitoplasma eritrosit sehingga mengganggu sistem protein.
Adanya timbal dalam peredaran darah dan dalam otak juga mengakibatkan berbagai gangguan fungsi jaringan dan metabolisme. Gangguan mulai dari sintesis haemoglobin darah, gangguan pada ginjal, sistem reproduksi, penyakit akut atau kronik sistem syaraf, serta gangguan fungsi paru-paru (Martaningtyas, 2004).
Timbal dan senyawanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan, sedangkan absorbsi melalui kulit sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Timbal yang diabsorsi diangkut oleh darah ke organ-organ tubuh sebanyak 95% Pb dalam darah diikat oleh eritrosit. Ekskresi Pb melalui urine sebanyak 75–80%, melalui feses 15% dan lainnya melalui empedu, keringat, rambut, dan kuku (Palar,1994).
Bahaya yang ditimbulkan oleh Pb tergantung oleh ukuran partikelnya. Partikel yang lebih kecil dari 10 µg dapat tertahan di paru-paru, sedangkan partikel yang lebih besar mengendap di saluran nafas bagian atas (Ardyanto, 2005). Dampak lebih jauh dari keracunan Pb adalah dapat menyebabkan hipertensi dan salah satu faktor penyebab penyakit hati. Ketika unsur ini mengikat kuat sejumlah molekul asam amino, haemoglobin, enzim, RNA, dan DNA maka akan mengganggu saluran metabolik dalam tubuh. Keracunan Pb dapat juga mengakibatkan gangguan sintesis darah, hipertensi, hiperaktivitas, dan kerusakan otak (Herman, 2006).
2.3 Rumput laut
Perairan Indonesia berpotensi besar untuk budidaya rumput laut dengan tehnik pengolahan yang mudah, penanganan yang sederhana dengan modal kecil sehingga di Indonesia berkembang industri pengolahan rumput laut. Salah satu di antaranya adalah PT. Bantimurung Indah Kab. Maros Sulawesi selatan yang mengolah rumput laut Jenis Euchema contonii dan Euchema spinosum (Yustin, dkk., 2005). Rumput laut atau yang biasa disebut dengan seaweed merupakan tanaman makroalga yang hidup di laut yang tidak memiliki akar, batang dan daun sejati dan pada umumnya hidup di dasar perairan. Rumput laut juga sering disebut sebagai alga atau ganggang pada daerah-daerah tertentu di Indonesia (Juneidi, 2004).
Menurut Afrianto dan Liviawati, (1993) fungsi dari akar, batang dan daun yang tidak dimiliki oleh rumput laut tersebut digantikan dengan thallus. Karena tidak memiliki akar, batang dan daun seperti umumnya pada tanaman, maka rumput laut digolongkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah (Thallophyta). Bagian–bagian rumput laut secara umum terdiri dari holdfast yaitu bagian dasar dari rumput laut yang berfungsi untuk menempel pada substrat dan thallus yaitu bentuk-bentuk pertumbuhan rumput laut yang menyerupai percabangan. Rumput laut memperoleh atau menyerap makanannya melalui sel-sel yang terdapat pada thallusnya. Nutrisi terbawa oleh arus air yang menerpa rumput laut akan diserap sehingga rumput laut bisa tumbuh dan berkembangbiak. Perkembangbiakan rumput laut melalui dua cara yaitu generatif dan vegetatif.
Gambar 1. Morfologi rumput laut (Afrianto dan Liviawati, 1993)
Ditinjau secara biologi, rumput laut merupakan kelompok tumbuhan yang berklorofil yang terdiri dari satu atau banyak sel dan berbentuk koloni. Di dalam alga terkandung bahan-bahan organik seperti polisakarida, hormon, vitamin, mineral dan juga senyawa bioaktif. Berbagai jenis alga seperti Griffithsia, Ulva, Enteromorpna, Gracilaria, Euchema, dan Kappaphycus telah dikenal luas sebagai sumber makanan seperti salad rumput laut atau sumber potensial karagenan yang dibutuhkan oleh industri gel. Begitupun dengan Sargassum, Chlorela/Nannochloropsis yang telah dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat (Putra, 2006).
Selain yang telah disebutkan di atas di dalam rumput laut juga terdapat mineral esensial (besi, iodin, aluminum, mangan, kalsium, nitrogen dapat larut, phosphor, sulfur, chlor. silikon, rubidium, strontium, barium, titanium, kobalt, boron, tembaga, kalium, dan unsur-unsur lainnya yang dapat dilacak), protein, tepung, gula dan vitamin A, D, C, D. Persentase kandungan zat-zat tersebut bervariasi tergantung dari jenisnya (Anonim, 2006). Pemanfaatan rumput laut yang demikian besarnya disebabkan dalam rumput laut terkandung beragam zat kimia dan bahan organik lain seperti vitamin (Hidayat, 1994).
Menurut Juneidi (2004), Alga merah merupakan kelompok alga yang jenis-jenisnya memiliki berbagai bentuk dan variasi warna salah satu indikasi dari alga merah adalah terjadi perubahan warna dari warna aslinya menjadi ungu atau merah apabila alga tersebut terkena panas atau sinar matahari secara langsung. Alga merah merupakan golongan alga yang mengandung karagenan dan agar yang bermanfaat untuk industri kosmetik dan makanan. Salah satu contoh rumput laut jenis alga merah yang bernilai ekonomis dan terdapat di perairan laut Indonesia adalah Eucheuma cottoni.
Ciri-ciri umum alga merah adalah :
- Bentuk thalli ada yang silindris (Gelidium latifolium), pipih (Gracillaria folifera) dan lembaran (Dictyopteris sp.)
- Warna thalli bervariasi ada yang merah (Dictyopteris sp.), pirang (Eucheuma spinosum), coklat (Acanthophora muscoides) dan hijau (Gracillaria gigas).
- Sistem percabangan thalli ada yang sederhana, kompleks,dan juga ada yang berselang – seling.
- Mengandung pigmen fotosintetik berupa karotin, xantofil, fikobilin, dan r-fikoeritrin penyebab warna merah dan klorofil a dan d.
Menurut Samsuari, (2006) beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut adalah fakor lingkungan yang meliputi:
1. Suhu
Pengaruh suhu terhadap sifat fisiologi organisme perairan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fotosintesis disamping cahaya dan konsentrasi fosfat. Perbedaan suhu terjadi karena adanya perbedaan energi matahari yang diterima oleh perairan. Suhu akan naik dengan meningkatnya energi matahari yang masuk ke dalam perairan. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan fotosintesis sampai pada radiasi tertentu. Kecepatan fotosintesis akan konstan dan produksi maksimum tidak tergantung pada energi matahari lagi sampai pada reaksi enzimatis. Fotosintesis maksimal bagi Eucheuma adalah pada suhu 21 – 31,2 oC, sedangkan pada suhu di atas 32 oC aktivitas fotosintesis terhambat.
2. Salinitas
Salinitas perairan berperan penting bagi organisme laut terutama dalam mengatur tekanan osmosis yang ada dalam tubuh organisme dengan cairan lingkungannya. Salinitas di perairan dipengaruhi oleh penguapan dan jumlah curah hujan. Salinitas tinggi terjadi jika curah hujan yang turun di suatu perairan kurang yang menyebabkan penguapan tinggi. Sebaliknya, jika curah hujan tinggi maka penguapan berkurang dan salinitas menjadi rendah.
3. Kecepatan arus
Pergerakan air mempengaruhi bobot, bentuk thallus dan produksi bahan-bahan hidrokoloid Eucheuma. Gerakan air (arus) yang baik untuk pertumbuhan rumput laut antara 20 – 40 cm/detik.
4. pH
Hampir seluruh alga mempunyai kisaran daya penyesuaian terhadap pH antara 6,8 – 9,6.
2.3.1 Eucheuma cottonii
Menurut Doty (1985) dalam Samsuari (2006), Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut merah (Rhodophyceae) dan berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. Maka jenis ini secara taksonomi disebut Kappaphycus alvarezii Nama daerah ‘cottonii’ umumnya lebih dikenal dan biasa dipakai dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional. Ciri fisik Eucheuma cottoni memiliki ciri-ciri yaitu Thallus silindris, permukaan licin, melekat pada sustrat dengan alat perekat berupa cakram (Juneidi, 2004), keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. (Aslan, 1998).
Lokasi budidaya rumput laut jenis ini di Indonesia antara lain Lombok, Sumba, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Kepulauan Seribu, dan Perairan Pelabuhan Ratu (Atmadja, 1996 dalam Samsuari 2006).
Klasifikasi Eucheuma cottonii menurut Doty (1985) dalam Samsuari (2006) adalah sebagai berikut :
Klasifikasi
Divisio/Phylum : Rhadophyta
Class : Rhodophyceae
Sub class : Florideophycidae
Ordo : Gigartinales
Famili : Soliericiae
Genus : Eucheuma
Spesies : Eucheuma cottonni (Kapaphycus alvarezii)
Gambar 2. Eucheuma cottoni (amsuari, 2006)
2.3.2 Rumput Laut sebagai Adsorben Logam Berat
Pemanfaatan sistem adsorpsi untuk pengambilan logam-logam berat dari perairan telah banyak dilakukan. Beberapa spesies alga telah ditemukan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mengadsorpsi ion-ion logam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk sel mati (biomassa). Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa gugus fungsi yang terdapat dalam alga mampu melakukan pengikatan dengan ion logam. Gugus fungsi tersebut terutama adalah gugus karboksil, hidroksil, sulfudril, amino, iomodazol, sulfat, dan sulfonat yang terdapat didalam dinding sel dalam sitoplasma (Putra, 2006). Rumput laut menawarkan keuntungan untuk biosorpsi karena memiliki struktur yang makroskopis sehingga dapat digunakan sebagai biosorben (Regine, dkk., 2000).
Dari berbagai penelitian di ketahui bahwa berbagai spesies alga terutama dari golongan alga hijau (Chlorophyta), alga coklat (Phaeophyta), dan alga merah (Rhodophyta) baik dalam keadaan hidup (sel hidup) maupun dalam bentuk sel mati (biomassa) dan biomassa terimmobilisasi telah mendapat perhatian untuk mengadsorpsi ion logam. Alga dalam keadaan hidup dimanfaatkan sebagai bioindikator tingkat pencemaran logam berat di lingkungan aquatik (perairan) sedangkan alga dalam bentuk biomassa dan biomassa terimmobilisasi dimanfaatkan sebagai biosorben (material biologi penyerap logam berat) dalam pengolahan air limbah (Putra, dkk., 2006).
Menurut Phillips (1980) makroalga merupakan indikator yang paling tepat dan efisien untuk pencemaran logam berat, karena mikroorganisme ini dapat mengakumulasi pencemar, terdapat dalam jumlah banyak, dan korelasi antara kandungan bahan pencemar dalam air dan dalam tubuh organisme dapat ditunjukkan.
Menurut Putra, dkk. (2006) keuntungan pemanfaatan alga sebagai bioindikator dan biosorben adalah:
(1) Alga mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam mengadsorpsi logam berat karena di dalam alga terdapat gugus fungsi yang dapat melakukan pengikatan dengan ion logam.
(2) Bahan bakunya mudah didapat dan tersedia dalam jumlah banyak
(3) Biaya operasional yang rendah
(4) Tidak perlu nutrisi tambahan
Gambar 3. Struktur sel dari Alga (Regine, dkk., 2000)
Mekanisme pengikatan ion-ion logam oleh alga terjadi melalui beberapa cara seperti adsorpsi melalui pertukaran ion, kompleksasi, serta entrapmen (Harris dan remelow 1990 dalam Raya 2001).
Ladeiro, dkk., (2006) menggunakan makroalga Cystoseira baccata sebagai biosorben untuk Cd(II) dan Pb(II) dengan studi kinetika dan kesetimbangan menunjukkan bahwa Cystoseira baccata mampu melakukan pengambilan logam dengan cepat, study kinetika dan kesetimbangan menunjukkan logam yang diserap sekitar 0.9 mmol/g ( 101mg/g untuk cadmium(II) dan 186 mg/g untuk dan lead(II) ) pada pH 4.5 Hashim dan Chu (2004) membandingkan besarnya kapasitas penyerapan logam cadmium oleh tiga jenis biomassa alga yaitu: alga coklat, alga merah, dan hijau. Hasil yang dioperoleh menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan maksimum pada pH 5 adalah alga merah < alga hijau < alga coklat, dengan kapasitas penyerapan sebesar 0,74 mmol/gram Sargassum baccularia (alga coklat) dan 0,48 mmol/gram Chaetomorphalinum (alga hijau) dan 0,23 mmol/gram Glcsilaria changii (alga merah). Dengan menggunakan model adsorpsi langmuir, Antunes, dkk., (2003) melaporkan bahwa biomassa Sargassum sp. potensial untuk menyerap ion Cu2+ dengan kapasitas penyerapan sebesar 1,48 mmol/g.
2.4 Adsorpsi
Adsorpsi adalah peristiwa terkonsentrasinya suatu zat pada permukaan zat lain. Zat yang menyerap disebut adsorben sedangkan zat yang diserap seperti molekul, atom atau ion disebut adsorbat (Laidler, 1982 dalam Tondok, 2001). Menurut Petrucci-Suminar (1987) terjadinya proses adsorpsi melibatkan gaya-gaya intermolekul seperti, gaya elektrostatik, gaya London serta antraksi ion-ion yang terdapat pada adsorben maupun adsorbat, sehingga proses adsorpsi akan melibatkan perubahan energi. Jika adsorpsi dipandang sebagai suatu reaksi kesetimbangan, maka pada keadaan setimbang ∆G = 0, sehingga energi adsorpsi dapat dirumuskan sebagai berikut :
-∆Go = -RT ln K (1)
Alberty dan Silbey (1992), menyatakan bahwa adsorpsi secara umum dapat didefinisikan sebagai akumulasi sejumlah molekul (senyawa, ion maupun atom) yang terjadi pada batas antara dua fasa. Adsorpsi dapat terjadi antara dua fasa seperti antara fasa cair-padat, fasa gas-padat, dan fasa gas-cair.
Berdasarkan besarnya interaksi antara adsorben dan adsorbat, maka adsorpsi dapat dibedakan menjadi adsorpsi kimiawi dan adsorpsi fisikawi. Adsorpsi kimia melibatkan pembentukan ikatan kimia, meskipun pada umumnya tidak ada perbedaan yang sangat jelas antara kedua jenis adsorpsi ini kecuali perubahan entalphinya dimana perubahan entalphi kimia lebih besar dari pada adsorpsi fisika yaitu berkisar 40 sampai 200 kj/mol. Adsorpsi kimia bergantung pada energi aktivasi (energi minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya adsorpsi). Besarnya energi adsorpsi menyebabkan adsorbat sangat sukar untuk dilepaskan dari permukaan adsorben, sedangkan banyaknya molekul yang teradsorpsi merupakan fungsi tekanan, konsentrasi dan suhu. Adsorpsi fisikawi merupakan proses yang sangat reversible, dengan waktu kesetimbangan yang tercapai segera setelah adsorbat bersentuhan dengan adsorben, di samping itu terjadi adsorpsi berlangsung dalam beberapa lapisan monomolekuler yang membutuhkan kondisi tekanan dan temperatur tertentu (Alberty dan Silbey 1992).
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut jenis Euchema cottonii, larutan induk Pb 1000 ppm, PbO2, aquades, dan air laut steril.
3.2 Alat
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat gelas yang umum digunakan di laboratorium, aerator, baskom (wadah untuk menumbuhkan rumput laut), tali, lampu neon, serta Spektropotometer Serapan Atom (SSA).
3.3 Waktu dan tempat pengambilan sampel
Pengambilan sampel dilakukan pada bulan maret 2008 di desa Gusungnge, Kel. Jalanjang, Kec.Gantarang, Kab.Bulukumba. Sampel ditumbuhkan di laboratorium kimia anorganik selama 45 hari.
3.4 Waktu dan Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2008 di laboratorium Kimia anorganik Universitas hasanuddin, Makassar
3.5 Prosedur Kerja
3.5.1 Pembuatan larutan induk Pb2+ 1000 ppm
Larutan induk Pb2+ 1000 ppm dibuat dengan cara melarutkan 1,1544 gram PbO2 dalam labu ukur 1000 mL.
3.5.2 Pembuatan Larutan Baku Timbal 100 Ppm
Larutan induk 1000 ppm dipipet 50 mL ke dalam labu ukur 500 mL, kemudian diimpitkan hingga tanda batas.
3.5.3 Penyiapan Media Pertumbuhan
3.5.3.1 Penyiapan Media Pertumbuhan Terkontaminasi Pb2+ 15 ppm
Larutan induk Pb2+ dipipet sebanyak 75 mL dan dimasukkan dalam wadah pertumbuhan yang berisi 5 L air laut.
3.5.3.2 Penyiapan Media Pertumbuhan Yang Terkontaminasi Pb2+ 5, 10,15 dan 20 ppm
Larutan induk Pb2+ 1000 ppm dipipet sebanyak 25 mL, 50 mL, 75 mL, dan 100 mL dan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi 5 L air laut.
3.5.4 Penentuan Kadar Timbal yang diserap oleh E.Cottoni berdasarkan waktu kontak
Euchema cottonii dicuci lalu dibersihkan dengan tissue, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram dalam berat basah. Euchema cottonii yang sudah ditimbang tersebut ditumbuhkan dalam wadah (baskom) yang telah diisi dengan 5 L air laut dan Pb2+ 15 ppm selama 45 hari. Selanjutnya diamati dan dicacat perubahan yang terjadi. Setiap hari ke-8 air laut yang digunakan menumbuhkan E.Cottonii dianalisis dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom.
3.5.1 Penyerapan Euchema cottonii terhadap Pb2+ berdasarkan variasi Konsentrasi
Euchema cottonii dicuci lalu dibersihkan dengan tissue, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram. Euchema cottonii yang sudah ditimbang tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam wadah (baskom) yang telah diisi dengan 5 L air laut dan Pb2+ 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm,20 ppm dan 25 ppm, lalu ditumbuhkan selama 45 hari. Diamati perubahan yang terjadi sampai pada hari ke 45. Air laut yang digunakan untuk menumbuhkan Euchema cottonii tersebut dianalisis menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom. Untuk menentukan kadar Pb2+ diserap oleh E.Cottoni dapat digunakan persamaan sebagai berikut:
Konsentrasi teradsorpsi = konsentrasi awal – konsentrasi akhir
Cadsorpsi = (Cawal – Cakhir)
Banyaknya ion-ion logam yang teradsorpsi (mg) per gram adsorben ditentukan menggunakan persamaan:
Keterangan:
Qe = jumlah ion logam yang teradsorpsi (mg/g)
C0 = konsentrasi ion logam sebelum adsorpsi
Ce = konsentrasi ion logam setelah adsorpsi
V = volume larutan ion logam (L)
Wa = jumlah adsorben, (g)
DAFTAR PUSTAKA
Afrianto, E. dan Liviawati, E., 1993, Budidaya Rumput Laut dan Cara Pengolahannya, Penerbit Bhratara, Jakarta.
Anonim, 2006 Menanggulangi Pencemaran Logam Berat (online), (http://www.ychi.org - ychi.org. diakses 4 Januari, 2008, pukul 09:35 Wita).
Anonim, 2006, Pesona rumput laut sebagai sumber devisa, (online) (http//www.dkp.go.id/content.php?c=3197, diakses 3 Februari 2008, pukul 20.15 wita).
Alberty, R.A. dan Silbey, R.J., 1992, Physical Chemistry, John Wiley & Sons, Inc, Canada.
Antunes, W.M., Luna, A.s., Henriques, C.A., dan Costa, A.C.A., 2003, An evaluation of copper biosorption by a brown seaweed under optimized conditions, Electronic J. of Biotechnology ISSN: 0717-3458.
Ardyanto D., 2005, Deteksi Pencemaran Timah Hitam (Pb) Dalam Darah Masyarakat Yang Terpajan Timbal (Plumbum), Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2 (1), 67 – 7.
Aslan, M., 1998, Budidaya Rumput Laut, Yogyakarta, Kanisius.
Bappedal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1997, Badan Pengendali Dampak Lingkungan, Jakarta.
Brahmana, S.S., dan Moelyo, M., 2003, Penelitian Bioremediasi Sumber Air Tercemar Bahan Berbahaya Dan Beracun, JLP. 17 (52), 83.
Darmono, 1995, Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup, UI-Press, Jakarta.
Davis, T. A., Volesky, B. dan Vieira, R. H. S. F., 2000, Sargassum Seaweed As Biosorbent For Heavy Metals, Wat. Res. Vol. 34 (17), 4270 – 4278.
Figueira, M. M. Volesky, B., Ciminelli, V. S. T. , dan Roddick, F. A., 2000, Biosorption Of Metals In Brown Seaweed Biomass, Wat. Res. 34 (1) 196 - 204
Herman, D.Z., 2006, Tinjauan Terhadap Tailing Mengandung Unsur Pencemar Arsen (As), Merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd) dari Sisa Pengolahan Bijih Logam, Jurnal Geologi Indonesia, 1 (1) 31-36.
Hidayat, A., 1994, Budidaya Rumput Laut, Usaha Nasimal, Surabaya.
Husain, D.R. dan Muchtar, I.H., 2005, Bakteri Pengompleks Logam Pb dan Cd Dari Limbah Cair PT. Kawasan Industri Makassar, Marina Chemica Acta, 7 (1), 25-28.
Hashim dan Chu, 2004, Biosorption of cadmium by brown, green, and red seaweeds, Chemical Engineering Journal, 97(2006) 249–255
Iqbal, H.Z. dan Qodir, M.A., 1990, AAS determination of Lead and Cadmium in Leaves Polluted by Vehicles Exhoust (Interface) Juornal Environmental Analytic Chemistry, 38 (4), 533 – 538.
Juneidi, W., 2004, Rumput Laut Jenis dan Morfologisnya, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Jakarta.
Lodeiro, P., Barriada, J.L., Herrero, R., dan Sastre de Vicente, M.E., 2005, The marine macroalga Cystoseira baccata as biosorbent for cadmium(II) and lead(II) removal: Kinetic and equilibrium studies, Environmental Pollution, 1 (142), 264-273.
Marganof, 2003, Potensi Limbah Udang Sebagai Penyerap Logam Berat (Timbal, Kadmium, dan tembaga) di Perairan, Makalah Pribadi Pengantar Ke Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor.
Martaningtyas, D., 2004, Bahaya Cemaran Logam Berat, (online) (http://www.pikiran-akyat.com/cetak/0704/29/cakrawala/lainnya08.htm, diakses 25 Desember 2007 pukul 11.00 Wita).
Nybakken, J.W., 1988, Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi, Gramedia, Jakarta.
Palar. H., 1994, Pencemaran dan Toksikologi logam berat, Rineka Cipta, Jakarta.
Phillips, D.J.H., 1980. Proposal for Monitoring Studies on Metals and Organochlorines. Dalam "South Chines Fisharies Development and Coordinating Programme". Manila: FAO.
Prihatiningsih, B., 2001, Studi Kinetika Penyisihan Logam Timbal (Pb) Pada Reaktor Biologi Anaerob Dengan Sistem Batch, (Online), (http://digilib.unikom.ac.id/go.php?id=jbptitbpp-gdl-s2-2001-bekti-1105-timbal, diakses pada tanggal 5 Januari 2008 pukul 11.30 Wita)
Putra, Buhani, dan Suharso, 2006, Alga sebagai Bioindikator dan Biosorben Logam Berat,(online) (http://www.chem-is-try.org/?sect=fokus&ext=29, diakses 20 desember 2007 pukul 09.00 Wita)
Putra S. E., 2006, Alga Laut sebagai Biotarget Industri, (online), (http://www.energi.lipi.go.id) diakses 20 desember 2007 pukul 09.20 Wita).
Petrucci-Suminar, 1987, Kimia Dasar, Prinsip dan Terapan Modern, edisi ke 4, Erlangga, Jakarta.
Rahman, A., 2006, Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Beberapa Jenis Krustasea Di Pantai Batakan dan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Bioscientiae, 3 (2), 93-101.
Regine, Vieira, dan Volesky B., 2000, Biosorption: a solution to pollution?, Internatl Microbiol, Canada.
Raya I., 2001, adsorpsi ion logam Tembaga(II) dan Cadmium(II) oleh Chaetoceros calcitrans hasil immobilisasi, FMIPA UNHAS, Makassar.
Sastrawijaya, A. T., 1991, Pencemaran Lingkungan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Samsuari, 2006, Karakterisasi karaginan Eucheuma cottonii pada berbagai umur panen, konsentrasi KOH dan lama ekstraksi. http://www.damandiri.or.id/file/samsuaripbbab3.pdfhttp://www.damandiri.or.id/file/samsuaripbbab3.pdf, diakses 28 januari 2008 .
Siahainenia, L., 2001, Pencemaran Laut Dampak dan Penanggulangannya, Makalah Falsafah Sains, Program Pascasarjana IPB, Bogor, (online), (http:www.hayati-ipb.com/users/rudyct/indiv2001/lauras.htm, diakses 9 Maret 2007, pukul 10.15 Wita).
Suhendrayatna, 2001, Bioremoval Logam Berat dengan Menggunakan Mikroorganisme: Suatu Kajian Kepustakaan, (online), http://www.istecs.org/publication/Japan/010211-Suhendrayatna.PDF, diakses 14 April 2007, 10.45 Wita).
Suryani, E. dan Liong, S., 2003, Distribusi Kuantitatif Logam Berat Pb, Cd dan Cu dalam sedimen di Sekitar Perairan laut Dangkal Pulau Sumbawa, Marina Chemica Acta, 5 (2), 2-8.
Sudrajad, A., 2006, Tumpahan Minyak di Laut dan Beberapa Catatan Terhadap Kasus di Indonesia, Inovasi, 6 (18), 1.
Tandjung, S.D., 1991, Konservasi Sumber Daya Alam, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tondok, L., 2001, Pemanfaatan limbah kulit kacang (Arachis hypogeae L.) sebagai adsorben ion tembaga(II) dalam air, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Kimia FMIPA UNHAS, Makassar
Yustin, D., Angelia, D., Hala, Y. dan Taba. P., 2005, Analisis Potensi Limbah Cair Hasil Pengolahan Rumput Laut Sebagai Pupuk Buatan, Marina Chemica Acta 7 (1), 2-8.
.
.
Lampiran 1. Bagan kerja penentuan kapasitas penyerapan E. Cottoni terhadap ion Pb2+ berdasarkan waktu kontak dan variasi konsentrasi.
Sabtu, 27 Maret 2010
Analisi Komponen Kandungan Kimia Pada Buah Merah
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Buah merah (Pandanus conoideus Lam) atau yang dikenal luas di Nabire dengan nama Biih Utaa adalah tanaman asli Papua yang tumbuh di dataran rendah (40 m dpl) sampai dataran tinggi (2.000 m dpl). Namun populasi terbanyak terdapat di dataran dengan ketinggian 1.200 hingga 2.000 m dpl. Buah merah biasa tumbuh bergerombol dalam satu area, jarang tumbuh menyendiri. Buah merah tumbuh di daerah dengan suhu di bawah 17 oC dengan curah hujan rata-rata 186 mm per bulan dan jumlah penyinaran matahari 57% dan tekanan udara rata-rata 896 mb. Tanaman Buah Merah termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan dgn pohon menyerupai pandan, namun tinggi tanaman dapat mencapai 16 m dengan tinggi batang bebas cabang sendiri setinggi 5 sampai 8 m yang diperkokoh akar-akar tunjang pada batang sebelah bawah. Kultivar buah berbentuk lonjong dgn kuncup tertutup daun buah. Buah Merah sendiri panjang buahnya mencapai 55 cm, diameter 10-15 cm, dan bobot 2-3 kg. Warnanya saat matang berwarna merah maroon terang. Walau sebenarnya ada jenis tanaman ini yg berbuah berwarna coklat dan coklat-kekuningan. Budidaya tanaman dipelopori oleh seorang warga lokal Nicolaas Maniagasi sejak tahun 1983, dan atas jerih payahnya tersebut mendapatkan penghargaan lingkungan hidup Kehati Buah merah sudah secara turun-temurun dikonsumsi oleh masyarakat Papua sebagai penambah energi dan daya tahan tubuh.
Masyarakat tradisional tahu buah merah berkhasiat, tetapi hanya sebagai obat cacing, penyakit kulit,dan menghambat kebutaan. Manfaat lain yang sudah dikenal hanyalah meningkatkan stamina. Buktinya masyarakat pedalaman Papua di Wamena memiliki postur tubuh kekar dan kuat. Buah merah juga menjadi menu sarapan wajib bagi sebagian besar anak sekolah di Puncak Jaya dan pedalaman Nabire. Tujuannya agar kondisi fisik tetap prima saat belajar.
Buah merah memiliki kandungan oksidan tinggi jadi wajar jika buah merah mampu menyembuhkan beragam penyakit. Harga buah merah ini amatlah mahal bahkan buah ini nilainya lebih mahal dari emas , padahal secara turun-temurun buah merah tak lebih dari sekedar bahan pangan masyarakat Papua. Dulu buah merah tak perlu dibeli.Kalaupun dibeli harganya amat murah. Sekarang sekali motret harganya Rp 2 juta.
Setelah diteliti ternyata buah merah terbukti ampuh menggempar HIV/AIDS, kanker,jantung koroner,hepatitis,dan penyakit lainnya . Jika anda membeli buah merah, buah merah ini dapat bertahan lama jika disimpan di dalam kulkas. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika anda mencobanya. Penulis mengangkat tema “Buah Merah si Multikhasiat” untuk mengenalkan, memberikan seputar informasi mengenai buah merah yang mempunyai banyak khasiat kepada masyarakat luar papua.
1.2 Maksud Penelitian
Maksud di lakukan penulisan ini adalah untuk melihat dan mengetahui komponen kandungan kimia pada buah merah dengan cara mengolah buah merah.
1.3 Tujuan Penenlitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Mengingatkan kepada masyarakat Papua untuk merawat buah merah
ini dengan baik ( tidak disia-siakan ).
b. Mengenalkan kepada masyarakat apakah buah merah itu.
c. Memberikan informasi kepada masyarakat manfaat dari buah merah.
d. Mengingatkan kita betapa berharganya kesehatan itu.
e. Mengingatkan kandungan kimia yang berada dalam buah kepada produsen
penjualan air buah merah.
f. Mengingatkan kita betapa banyaknya obat alami di alam sekitar kita yang belum
dimanfaatkan dengan baik.
1.4 Manfaat dan Kegunaan
a. Menyimak manfaat buah merah
b. Menemukan cara memanfaatkan buah merah
c. Mengetahui Komponen kandungan kimia dalam sari buah merah
d. Mengetahui pentingnya hidup sehat
e. Mengetahui keampuhan buah merah bagi penyakit ganas.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengenalan Buah Merah
Buah merah (Pandanus conoideus) atau yang dikenal luas di Nabire dengan nama Biih Utaa adalah tanaman asli Papua yang tumbuh di dataran rendah (40 m dpl) sampai dataran tinggi (2.000 m dpl). Namun populasi terbanyak terdapat di dataran dengan ketinggian 1.200 hingga 2.000 m dpl. Buah merah biasa tumbuh bergerombol dalam satu area, jarang tumbuh menyendiri. Buah merah tumbuh di daerah dengan suhu di bawah 17 oC dengan curah hujan rata-rata 186 mm per bulan dan jumlah penyinaran matahari 57% dan tekanan udara rata-rata 896 mb. Tanaman Buah Merah termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan dgn pohon menyerupai pandan, namun tinggi tanaman dapat mencapai 16 m dengan tinggi batang bebas cabang sendiri setinggi 5 sampai 8 m yang diperkokoh akar-akar tunjang pada batang sebelah bawah. Kultivar buah berbentuk lonjong dgn kuncup tertutup daun buah. Buah Merah sendiri panjang buahnya mencapai 55 cm, diameter 10-15 cm, dan bobot 2-3 kg. Warnanya saat matang berwarna merah maroon terang. Walau sebenarnya ada jenis tanaman ini yg berbuah berwarna coklat dan coklat-kekuningan. Budidaya tanaman dipelopori oleh seorang warga lokal Nicolaas Maniagasi sejak tahun 1983, dan atas jerih payahnya tersebut mendapatkan penghargaan lingkungan hidup Kehati Award 2002. Buah merah sudah secara turun-temurun dikonsumsi oleh masyarakat Papua sebagai penambah energi dan daya tahan tubuh.
2.2. Cara Memilih Buah Merah
Sebenarnya buah merah yang patut di konsumsi oleh maysarakat kita ialah buah merah yang produksi langsung dari Papua. Sebab kandungan tertinggi seperti alkaloid, fenol dan glikosida dsb biasaya terdapat pada buah merah yang tumbuh di Pegunungan dengan ketinggian sesuai , yang mana saat ini hanya di temukan di Pegunungan Nabire
Ciri dari buah merah yang berkasiat ialah buah merah yang telah matang dan bentuknya kurang lebih membentuk semacam lampu, buah merah yang demikan yang memang benar-benar berkhasiat.
Foto Buah merah.
2.3 Habitat
Berbicara habitat, memang banyak dari para produsen saat ini berlomba-lomba mencari daerah habitat buah merah di luar papua dengan mengkesampingkan mutu.
Berdasarkan survei ada beberapa produsen besar yang mana untuk mendapatkan buah merah ini, mereka khusus mendatangkan kapal dan mulai untuk memanen buah merah secara massal dan besar-besaran dari sekitar halmahera utara dan sekitarnya.
Namun upaya ini sebenarnya merupakan langkah bunuh diri bagi perusahaan yang bersangkutan, sebab pada habitat buah merah yang diambil dari daerah pesisir , tidak mengandung senyawa-senyawa antioksidan yang terbukti saat ini , berpotensi untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Sehingga jelas bahwa orientasi perusahaan yang demikian memang hanyalah pada margin keuntungan dengan menomorduakan kualitas. Bahkan saat kami tanya pada penduduk setempat mengenai kegunaan buah tersebut, banyak dari mereka mengatakan bahwa buah merah tersebut , selama ini hanya dijadikan sebagai komoditas untuk bahan baku pewarna, namun karena permintaan dari produsen maka tidak ada alasan bagi mereka untuk memanen buah merah tersebut untuk para produsen.
Tetapi yang mengherankan adalah justru banyak dari konsumen yang lebih membeli harga dari pada membeli kualitas, padahal konsumen yang demikian tidak ubahnya dengan membeli pewarna merah dengan harga yang cukup mahal (hati hati dengan produk yang tidak jelas, karena kesalahan dalam proses pembuatan minyak buah merah dapat menyebabkan efek samping berupa alergi, gatal gatal, dan gangguan pencernaan).
2.4. Kemurnian Produk
Dengan menjamurnya produsen Sari Buah Merah terutama dikota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bogor dan Bandung, sulit untuk menentukan mana produksi yang benar berkualitas, murni dan terjamin keasliannya. Kemasan botol gelas yang lux bukanlah jaminan produk tersebut murni. Janganlah cepat percaya kata-kata asli, sebelum membeli dalam jumlah besar cobalah untuk membeli ukuran kecil dan buktikan kemurniannyadengancara :Menyimpan di almari es (bukan frezzer)
Bila memang ternyata membeku, maka jelas produk yang anda beli di campur minyak goreng/minyak zaitun/atau zat lain, Ada yang mengatakan buah merah bagus bila di campur dengan minyak zaitun, padahal pencampuran buah merah dengan bahan lain seperti minyak goreng menjadikan campuran tersebut menjadi minyak jenuh.
Secara umum penyampuran tersebut dapat berbahaya khususnya bagi penderita asma, sirosis, gangguanparu-paru.
MenelitidenganMenyinari
Bila dilihat dengan menyinar sari buah merah yang murni jernih dan tembus pandang. Bila cairan mengandung campuran, saat kita senter botol tidak akan terlihat tembus pandang, banyak serat atau pasta. Sisa pasta ini menyebabkan buah merah cepat membusuk, seperti halnya buah mengkudu atau noni yang harus di habiskan dengan segera. Untuk buah merah murni pada umunya lebih lama masa pembusukannya. Perhatikan juga adanya Expiry Date pada botol untuk menunjukkan masa berlaku produk tersebut.
Meneliti Melalui Aroma
Untuk Sari Buah Merah asli biasanya aroma seperti wijen akan tercium kuat ini penting dicek sebab diantara kelima perusahaan yang menerima Depkes, ada yang aroma wijennya sedikit (kemungkinan ada zat aditif untuk menambah jumlah). Disamping itu minyak sari buah merah viskositasnya lebih rendah dari minyak goreng (minyak goreng terlihat lebih kental)
Generalisasi
Kandungan Zat berkhasiat yang terdapat di dalam buah merah merupakan hal terpenting saat anda membeli suatu produk. Untuk itu disarankan untuk membeli produk yang benar-benar diproduksi di Papua/dikemas dan dibotolkan di Papua karena proses
yang dilakukan di tempat lain (di Jakarta dll) akan menambah kemungkinan tidak murninya SariBuahMerahyang kita beli.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.Metode Penelitian
Dalam menyelesaikan Makalah ini penulis memakai metode penelitian yang menggunakan studi pustaka yaitu mencari sumber dari bacaan ( Majalah, Buku, Artikel, Koran, Telaa pustaka,dan Media Elektronik (Internet).
3.2 Cara Mengolah Buah Merah
Cara mengolah buah merah hingga menjadi obat tidaklah sulit. Setelah dicuci hingga bersih, buah merah dibelah dua untuk dibuang getahnya. Setelah itu, buah direbus dalam air sekitar satu jam atau sampai buah mengeluarkan cairan merah seperti tinta jika ditekan – tekan kulitnya. Jika sudah demikian, buah sudah bisa diremas – remas untuk mendapatkan cairan merahnya. Cairan merah ditampung dalam sebuah gelas dan siap diminum. Mengonsumsi buah merah ini secara rutin diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit ganas.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Zat-zat komponen kimia yang terkandung pada buah merah
Sampai saat ini senyawa kimia yang terkandung di dalam sari buah merah masih tidak seragam, terutama tokoferol dan betakarotennya. Beberapa sampel sari buah merah yang diteliti menunjukkan kadar kandungan tokoferol dan betakaroten yang berbeda-beda. Jumlah kandungan dua senyawa ini dipengaruhi oleh tempat tumbuh tanaman dan proses pembuatannya. Tokoferol dan betakaroten yang tinggi diperoleh dari buah yang berasal dari tanaman dataran tinggi dan melalui proses pemasakan yang benar. Proses pemasakan dengan pemanasan tinggi dan waktu lama akan menurunkan dua kandungan tersebut. Kandungan senyawa kimia ini juga dipengaruhi oleh jenis buah merah tersebut. Dipedalaman Papua sendiri bisa ditemukan paling sedikit 14 jenis atau varietas tanaman buah merah.
a) Senyawa antioksidan
Senyawa antioksidan buah merah tergolong tinggi. Lihat saja, dari 12.000 ppm total karotenoid, sebanyak 700 ppm di antaranya berupa betakaroten. Sedangkan tokoferol mencapai 11.000 ppm. Dengan begitu buah merah memiliki efek antikanker yang kuat
b) Betakaroten
Betakaroten berfungsi memperlambat berlangsungnya penumpukan flek pada arteri sehingga aliran darah, baik ke jantung maupun ke otak, bisa berlangsung lancar, tanpa sumbatan. Ia juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh karena interaksi vitamin A dengan protein (asam – asam) amino yang berperan dalam pembentukan antibody.
c) Tokoferol
Tingginya vitamin E – nama lain tokoferol – hanya dapat ditandingi oleh zaitun. Senyawa itulah benteng pertahanan terhadap serangan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, darah tinggi, dan kanker. Fungsi tokoferol ibarat pemadam kebakaran yang mematikan serbuan radikal bebas dan menetralisir kolesterol dalam darah. Bersama – sama sel limfosit dan mononuklear, senyawa aktif itu memperbaiki sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi modoritas dan moralitas sel tubuh. Ia pun membantu pembentukan sel – sel baru untuk menggantikan sel – sel rusak atau tua. Tokoferol menurunkan kadar LDL – kolesterol dan meningkatkan kadar HDL – kolesterol, ia membantu hati memproduksi asam – asam empedu dan hormon – hormon penting.
d) Asam lemak
Asam lemak dalam buah merah juga merupakan antibiotik dan antivirus alami yang kuat. Mereka aktif melemahkan dan meluruhkan membran lipida virus serta mematikannya, ia efektif menghambat dan membunuh beragam strain virus, termasuk
virus hepatitis yang merusak sel hati., ia juga terbukti menghambat dan membunuh sel – sel tumor aktif
4.1.2 Kandungan Komponen Kimia Pada Buah Merah
a. Daftar kandungan senyawa aktif komponen kimia pada buah merah
Berikut ini adalah daftar kandungan senyawa aktif asam amino dalam sari buah merah.
Tabel 1. Komposisi Kandungan Kimia
No Kandungan Senyawa Aktif Sari Buah Merah Jumlah Kandungan
1 Total Karotenoid 12.000 ppm
2 Total Tokoferol 11.000 ppm
3 Betakaroten 700 ppm
4 Alfa tokoferol 500 ppm
5 Asam oleat 58 %
6 Asam linoleat 8,8 %
7 Asam linolenat 7,8 %
8 Dekanoat 2,0 %
Tabel 2. Daftar komposisi gizi pada buah merah
No Daftar koposisi gizi per 100 gr Buah merah Kandungan gizi
1 Enegi 396 kalori
2 Protein 396 kalori
3 Lemak 28.100 mg
4 Serat 20.900 mg
5 Kalsium 54.000 mg
6 Fosfor 30 mg
7 Besi 2,44 mg
8 Vitamin B1 0,90 mg
9 Vitamin C 25,70 mg
10 Nialin 1,8 mg
11 Air 34,90 %
4.1.3 Pembahasann
Berdasarkan Tabel penelitian analisis komponen kimia yang di lakukan, Buah merah mengandung komposisi gizi lengkap. Dan buah merah pun memiliki zat-zat aktif seperti Betakaroten, Tokoferol,dan sejumlah asam lemak esensial. Selain itu buah merah juga mangandung Vitamin dan mineral esensial yang cukup lengkap. Diantaranya; Fosfor,Besi,Vitamin B1, Vitamin C , dan Nialin. Kandungan energi cukup tinggi,mencapai 400 kalori/100 gram.
Dari analisis kimia yang dilakukan Maka di peroleh hasil bahwa, buah merah mengandung komposisi gizi lengkap. Ia memiliki zat – zat aktif seperti betakaroten, tokoferol, dan sejumlah asam lemak esensial. Selain itu buah merah juga mengndung vitamin dan mineral esensial yang cukup lengkap. Di antaranya kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, vitamin C, dan nialin. Kandungan energi cukup tinggi, mencapai 400 kalori / 100 gram daging buah.
BAB V
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat di lihat bahwa pada buah merah banyak mengandung kandungan kimia terutama Betakaroten, Tokoferol, Senyawa Anti Oksidan, dan Asam lemak. Dan asam amino yang terdapat pada buah merah adalah asam amino esensial.
Jadi buah merah bisa di manfaatkan sebagai obat dari berbagai penyakit seperti:
1. Korestrol
2. Reumathik
3. Asam urat
4. Sakit maag
5. Asma
6. HIV AIDS
DAFTAR PUSTAKA
Search Google http// www Papua Online. Com. Penentuan Komponen Kimia Pada Buah
Merah. Akses tgl 3 Mei, 2008, Jam 19 :25 Wit.
Search Google http// www. Kabar Papua. Penentuan Komponen Kimia Dan Kandungan
Gizi Pada Buah Merah. Diakses tgl 19 Juli,2008 pukul 20 : 21 Wit di Makassar.
Sudarmadji, S., dkk,1989, Analisa Bahan Makanan Dan Komponen Kandungan Kimia.
Liberty, Yogyakarta.
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN Halaman
1.1. Latar Belakang…………………………………………………………... 1
1.2. Maksud………………………………………………………………….. 2
1.3. Tujuan……………………………………………………………………. 2
1.4. Manfaat………………………………………………………………….. 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1.Pengenalan Buah Merah…………………………………………………. 4
2.2. Cara Memilih Buah Merah………………………………………………. 4
2.3.Habitat…………………………………………………………………….. 5
2.4. Kemurnian Produk……………………………………………………….. 6
BAB III METODE PENELITIAN 7
3.1.Metode Penelitian………………………………………………………….7
3.2 Cara mengolah Buah Merah……………………………………………... 7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 8
4.1.1.Zat-zat komponen kimia yang terkandung pada buah merah………… 8
a.senyanwa anti oksida……………………………………………… 8
b.Betakaroten……………………………………………………….. 8
c. Tokoferol………………………………………………………… 9
d.Asam lemak………………………………………………………. 9
4.1.2 Kandungan Komponen Kimia Pada Buah Merah…………………… 10
Tabel 1. KomposisiKandungan Kimia……………………………………. 10
Tabel 3. Daftar komposisi gizi pada buah merah……………………………11
4.1.3 Pembahasan …………………………………………………………. 11
BAB V KESIMPULAN 12
Kesimpulan……………………………………………………………………… 13
DAFTAR PUSTAKA 14
ANALISIS KOMPONEN KANDUNGAN KIMIA PADA BUAH MERAH
(Pandanus Conoideus. Lam)
Oleh
Yusuf Pekei
H31 106 205
JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERTSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Buah merah (Pandanus conoideus Lam) atau yang dikenal luas di Nabire dengan nama Biih Utaa adalah tanaman asli Papua yang tumbuh di dataran rendah (40 m dpl) sampai dataran tinggi (2.000 m dpl). Namun populasi terbanyak terdapat di dataran dengan ketinggian 1.200 hingga 2.000 m dpl. Buah merah biasa tumbuh bergerombol dalam satu area, jarang tumbuh menyendiri. Buah merah tumbuh di daerah dengan suhu di bawah 17 oC dengan curah hujan rata-rata 186 mm per bulan dan jumlah penyinaran matahari 57% dan tekanan udara rata-rata 896 mb. Tanaman Buah Merah termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan dgn pohon menyerupai pandan, namun tinggi tanaman dapat mencapai 16 m dengan tinggi batang bebas cabang sendiri setinggi 5 sampai 8 m yang diperkokoh akar-akar tunjang pada batang sebelah bawah. Kultivar buah berbentuk lonjong dgn kuncup tertutup daun buah. Buah Merah sendiri panjang buahnya mencapai 55 cm, diameter 10-15 cm, dan bobot 2-3 kg. Warnanya saat matang berwarna merah maroon terang. Walau sebenarnya ada jenis tanaman ini yg berbuah berwarna coklat dan coklat-kekuningan. Budidaya tanaman dipelopori oleh seorang warga lokal Nicolaas Maniagasi sejak tahun 1983, dan atas jerih payahnya tersebut mendapatkan penghargaan lingkungan hidup Kehati Buah merah sudah secara turun-temurun dikonsumsi oleh masyarakat Papua sebagai penambah energi dan daya tahan tubuh.
Masyarakat tradisional tahu buah merah berkhasiat, tetapi hanya sebagai obat cacing, penyakit kulit,dan menghambat kebutaan. Manfaat lain yang sudah dikenal hanyalah meningkatkan stamina. Buktinya masyarakat pedalaman Papua di Wamena memiliki postur tubuh kekar dan kuat. Buah merah juga menjadi menu sarapan wajib bagi sebagian besar anak sekolah di Puncak Jaya dan pedalaman Nabire. Tujuannya agar kondisi fisik tetap prima saat belajar.
Buah merah memiliki kandungan oksidan tinggi jadi wajar jika buah merah mampu menyembuhkan beragam penyakit. Harga buah merah ini amatlah mahal bahkan buah ini nilainya lebih mahal dari emas , padahal secara turun-temurun buah merah tak lebih dari sekedar bahan pangan masyarakat Papua. Dulu buah merah tak perlu dibeli.Kalaupun dibeli harganya amat murah. Sekarang sekali motret harganya Rp 2 juta.
Setelah diteliti ternyata buah merah terbukti ampuh menggempar HIV/AIDS, kanker,jantung koroner,hepatitis,dan penyakit lainnya . Jika anda membeli buah merah, buah merah ini dapat bertahan lama jika disimpan di dalam kulkas. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika anda mencobanya. Penulis mengangkat tema “Buah Merah si Multikhasiat” untuk mengenalkan, memberikan seputar informasi mengenai buah merah yang mempunyai banyak khasiat kepada masyarakat luar papua.
1.2 Maksud Penelitian
Maksud di lakukan penulisan ini adalah untuk melihat dan mengetahui komponen kandungan kimia pada buah merah dengan cara mengolah buah merah.
1.3 Tujuan Penenlitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Mengingatkan kepada masyarakat Papua untuk merawat buah merah
ini dengan baik ( tidak disia-siakan ).
b. Mengenalkan kepada masyarakat apakah buah merah itu.
c. Memberikan informasi kepada masyarakat manfaat dari buah merah.
d. Mengingatkan kita betapa berharganya kesehatan itu.
e. Mengingatkan kandungan kimia yang berada dalam buah kepada produsen
penjualan air buah merah.
f. Mengingatkan kita betapa banyaknya obat alami di alam sekitar kita yang belum
dimanfaatkan dengan baik.
1.4 Manfaat dan Kegunaan
a. Menyimak manfaat buah merah
b. Menemukan cara memanfaatkan buah merah
c. Mengetahui Komponen kandungan kimia dalam sari buah merah
d. Mengetahui pentingnya hidup sehat
e. Mengetahui keampuhan buah merah bagi penyakit ganas.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengenalan Buah Merah
Buah merah (Pandanus conoideus) atau yang dikenal luas di Nabire dengan nama Biih Utaa adalah tanaman asli Papua yang tumbuh di dataran rendah (40 m dpl) sampai dataran tinggi (2.000 m dpl). Namun populasi terbanyak terdapat di dataran dengan ketinggian 1.200 hingga 2.000 m dpl. Buah merah biasa tumbuh bergerombol dalam satu area, jarang tumbuh menyendiri. Buah merah tumbuh di daerah dengan suhu di bawah 17 oC dengan curah hujan rata-rata 186 mm per bulan dan jumlah penyinaran matahari 57% dan tekanan udara rata-rata 896 mb. Tanaman Buah Merah termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan dgn pohon menyerupai pandan, namun tinggi tanaman dapat mencapai 16 m dengan tinggi batang bebas cabang sendiri setinggi 5 sampai 8 m yang diperkokoh akar-akar tunjang pada batang sebelah bawah. Kultivar buah berbentuk lonjong dgn kuncup tertutup daun buah. Buah Merah sendiri panjang buahnya mencapai 55 cm, diameter 10-15 cm, dan bobot 2-3 kg. Warnanya saat matang berwarna merah maroon terang. Walau sebenarnya ada jenis tanaman ini yg berbuah berwarna coklat dan coklat-kekuningan. Budidaya tanaman dipelopori oleh seorang warga lokal Nicolaas Maniagasi sejak tahun 1983, dan atas jerih payahnya tersebut mendapatkan penghargaan lingkungan hidup Kehati Award 2002. Buah merah sudah secara turun-temurun dikonsumsi oleh masyarakat Papua sebagai penambah energi dan daya tahan tubuh.
2.2. Cara Memilih Buah Merah
Sebenarnya buah merah yang patut di konsumsi oleh maysarakat kita ialah buah merah yang produksi langsung dari Papua. Sebab kandungan tertinggi seperti alkaloid, fenol dan glikosida dsb biasaya terdapat pada buah merah yang tumbuh di Pegunungan dengan ketinggian sesuai , yang mana saat ini hanya di temukan di Pegunungan Nabire
Ciri dari buah merah yang berkasiat ialah buah merah yang telah matang dan bentuknya kurang lebih membentuk semacam lampu, buah merah yang demikan yang memang benar-benar berkhasiat.
Foto Buah merah.
2.3 Habitat
Berbicara habitat, memang banyak dari para produsen saat ini berlomba-lomba mencari daerah habitat buah merah di luar papua dengan mengkesampingkan mutu.
Berdasarkan survei ada beberapa produsen besar yang mana untuk mendapatkan buah merah ini, mereka khusus mendatangkan kapal dan mulai untuk memanen buah merah secara massal dan besar-besaran dari sekitar halmahera utara dan sekitarnya.
Namun upaya ini sebenarnya merupakan langkah bunuh diri bagi perusahaan yang bersangkutan, sebab pada habitat buah merah yang diambil dari daerah pesisir , tidak mengandung senyawa-senyawa antioksidan yang terbukti saat ini , berpotensi untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Sehingga jelas bahwa orientasi perusahaan yang demikian memang hanyalah pada margin keuntungan dengan menomorduakan kualitas. Bahkan saat kami tanya pada penduduk setempat mengenai kegunaan buah tersebut, banyak dari mereka mengatakan bahwa buah merah tersebut , selama ini hanya dijadikan sebagai komoditas untuk bahan baku pewarna, namun karena permintaan dari produsen maka tidak ada alasan bagi mereka untuk memanen buah merah tersebut untuk para produsen.
Tetapi yang mengherankan adalah justru banyak dari konsumen yang lebih membeli harga dari pada membeli kualitas, padahal konsumen yang demikian tidak ubahnya dengan membeli pewarna merah dengan harga yang cukup mahal (hati hati dengan produk yang tidak jelas, karena kesalahan dalam proses pembuatan minyak buah merah dapat menyebabkan efek samping berupa alergi, gatal gatal, dan gangguan pencernaan).
2.4. Kemurnian Produk
Dengan menjamurnya produsen Sari Buah Merah terutama dikota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bogor dan Bandung, sulit untuk menentukan mana produksi yang benar berkualitas, murni dan terjamin keasliannya. Kemasan botol gelas yang lux bukanlah jaminan produk tersebut murni. Janganlah cepat percaya kata-kata asli, sebelum membeli dalam jumlah besar cobalah untuk membeli ukuran kecil dan buktikan kemurniannyadengancara :Menyimpan di almari es (bukan frezzer)
Bila memang ternyata membeku, maka jelas produk yang anda beli di campur minyak goreng/minyak zaitun/atau zat lain, Ada yang mengatakan buah merah bagus bila di campur dengan minyak zaitun, padahal pencampuran buah merah dengan bahan lain seperti minyak goreng menjadikan campuran tersebut menjadi minyak jenuh.
Secara umum penyampuran tersebut dapat berbahaya khususnya bagi penderita asma, sirosis, gangguanparu-paru.
MenelitidenganMenyinari
Bila dilihat dengan menyinar sari buah merah yang murni jernih dan tembus pandang. Bila cairan mengandung campuran, saat kita senter botol tidak akan terlihat tembus pandang, banyak serat atau pasta. Sisa pasta ini menyebabkan buah merah cepat membusuk, seperti halnya buah mengkudu atau noni yang harus di habiskan dengan segera. Untuk buah merah murni pada umunya lebih lama masa pembusukannya. Perhatikan juga adanya Expiry Date pada botol untuk menunjukkan masa berlaku produk tersebut.
Meneliti Melalui Aroma
Untuk Sari Buah Merah asli biasanya aroma seperti wijen akan tercium kuat ini penting dicek sebab diantara kelima perusahaan yang menerima Depkes, ada yang aroma wijennya sedikit (kemungkinan ada zat aditif untuk menambah jumlah). Disamping itu minyak sari buah merah viskositasnya lebih rendah dari minyak goreng (minyak goreng terlihat lebih kental)
Generalisasi
Kandungan Zat berkhasiat yang terdapat di dalam buah merah merupakan hal terpenting saat anda membeli suatu produk. Untuk itu disarankan untuk membeli produk yang benar-benar diproduksi di Papua/dikemas dan dibotolkan di Papua karena proses
yang dilakukan di tempat lain (di Jakarta dll) akan menambah kemungkinan tidak murninya SariBuahMerahyang kita beli.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.Metode Penelitian
Dalam menyelesaikan Makalah ini penulis memakai metode penelitian yang menggunakan studi pustaka yaitu mencari sumber dari bacaan ( Majalah, Buku, Artikel, Koran, Telaa pustaka,dan Media Elektronik (Internet).
3.2 Cara Mengolah Buah Merah
Cara mengolah buah merah hingga menjadi obat tidaklah sulit. Setelah dicuci hingga bersih, buah merah dibelah dua untuk dibuang getahnya. Setelah itu, buah direbus dalam air sekitar satu jam atau sampai buah mengeluarkan cairan merah seperti tinta jika ditekan – tekan kulitnya. Jika sudah demikian, buah sudah bisa diremas – remas untuk mendapatkan cairan merahnya. Cairan merah ditampung dalam sebuah gelas dan siap diminum. Mengonsumsi buah merah ini secara rutin diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit ganas.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Zat-zat komponen kimia yang terkandung pada buah merah
Sampai saat ini senyawa kimia yang terkandung di dalam sari buah merah masih tidak seragam, terutama tokoferol dan betakarotennya. Beberapa sampel sari buah merah yang diteliti menunjukkan kadar kandungan tokoferol dan betakaroten yang berbeda-beda. Jumlah kandungan dua senyawa ini dipengaruhi oleh tempat tumbuh tanaman dan proses pembuatannya. Tokoferol dan betakaroten yang tinggi diperoleh dari buah yang berasal dari tanaman dataran tinggi dan melalui proses pemasakan yang benar. Proses pemasakan dengan pemanasan tinggi dan waktu lama akan menurunkan dua kandungan tersebut. Kandungan senyawa kimia ini juga dipengaruhi oleh jenis buah merah tersebut. Dipedalaman Papua sendiri bisa ditemukan paling sedikit 14 jenis atau varietas tanaman buah merah.
a) Senyawa antioksidan
Senyawa antioksidan buah merah tergolong tinggi. Lihat saja, dari 12.000 ppm total karotenoid, sebanyak 700 ppm di antaranya berupa betakaroten. Sedangkan tokoferol mencapai 11.000 ppm. Dengan begitu buah merah memiliki efek antikanker yang kuat
b) Betakaroten
Betakaroten berfungsi memperlambat berlangsungnya penumpukan flek pada arteri sehingga aliran darah, baik ke jantung maupun ke otak, bisa berlangsung lancar, tanpa sumbatan. Ia juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh karena interaksi vitamin A dengan protein (asam – asam) amino yang berperan dalam pembentukan antibody.
c) Tokoferol
Tingginya vitamin E – nama lain tokoferol – hanya dapat ditandingi oleh zaitun. Senyawa itulah benteng pertahanan terhadap serangan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, darah tinggi, dan kanker. Fungsi tokoferol ibarat pemadam kebakaran yang mematikan serbuan radikal bebas dan menetralisir kolesterol dalam darah. Bersama – sama sel limfosit dan mononuklear, senyawa aktif itu memperbaiki sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi modoritas dan moralitas sel tubuh. Ia pun membantu pembentukan sel – sel baru untuk menggantikan sel – sel rusak atau tua. Tokoferol menurunkan kadar LDL – kolesterol dan meningkatkan kadar HDL – kolesterol, ia membantu hati memproduksi asam – asam empedu dan hormon – hormon penting.
d) Asam lemak
Asam lemak dalam buah merah juga merupakan antibiotik dan antivirus alami yang kuat. Mereka aktif melemahkan dan meluruhkan membran lipida virus serta mematikannya, ia efektif menghambat dan membunuh beragam strain virus, termasuk
virus hepatitis yang merusak sel hati., ia juga terbukti menghambat dan membunuh sel – sel tumor aktif
4.1.2 Kandungan Komponen Kimia Pada Buah Merah
a. Daftar kandungan senyawa aktif komponen kimia pada buah merah
Berikut ini adalah daftar kandungan senyawa aktif asam amino dalam sari buah merah.
Tabel 1. Komposisi Kandungan Kimia
No Kandungan Senyawa Aktif Sari Buah Merah Jumlah Kandungan
1 Total Karotenoid 12.000 ppm
2 Total Tokoferol 11.000 ppm
3 Betakaroten 700 ppm
4 Alfa tokoferol 500 ppm
5 Asam oleat 58 %
6 Asam linoleat 8,8 %
7 Asam linolenat 7,8 %
8 Dekanoat 2,0 %
Tabel 2. Daftar komposisi gizi pada buah merah
No Daftar koposisi gizi per 100 gr Buah merah Kandungan gizi
1 Enegi 396 kalori
2 Protein 396 kalori
3 Lemak 28.100 mg
4 Serat 20.900 mg
5 Kalsium 54.000 mg
6 Fosfor 30 mg
7 Besi 2,44 mg
8 Vitamin B1 0,90 mg
9 Vitamin C 25,70 mg
10 Nialin 1,8 mg
11 Air 34,90 %
4.1.3 Pembahasann
Berdasarkan Tabel penelitian analisis komponen kimia yang di lakukan, Buah merah mengandung komposisi gizi lengkap. Dan buah merah pun memiliki zat-zat aktif seperti Betakaroten, Tokoferol,dan sejumlah asam lemak esensial. Selain itu buah merah juga mangandung Vitamin dan mineral esensial yang cukup lengkap. Diantaranya; Fosfor,Besi,Vitamin B1, Vitamin C , dan Nialin. Kandungan energi cukup tinggi,mencapai 400 kalori/100 gram.
Dari analisis kimia yang dilakukan Maka di peroleh hasil bahwa, buah merah mengandung komposisi gizi lengkap. Ia memiliki zat – zat aktif seperti betakaroten, tokoferol, dan sejumlah asam lemak esensial. Selain itu buah merah juga mengndung vitamin dan mineral esensial yang cukup lengkap. Di antaranya kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, vitamin C, dan nialin. Kandungan energi cukup tinggi, mencapai 400 kalori / 100 gram daging buah.
BAB V
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat di lihat bahwa pada buah merah banyak mengandung kandungan kimia terutama Betakaroten, Tokoferol, Senyawa Anti Oksidan, dan Asam lemak. Dan asam amino yang terdapat pada buah merah adalah asam amino esensial.
Jadi buah merah bisa di manfaatkan sebagai obat dari berbagai penyakit seperti:
1. Korestrol
2. Reumathik
3. Asam urat
4. Sakit maag
5. Asma
6. HIV AIDS
DAFTAR PUSTAKA
Search Google http// www Papua Online. Com. Penentuan Komponen Kimia Pada Buah
Merah. Akses tgl 3 Mei, 2008, Jam 19 :25 Wit.
Search Google http// www. Kabar Papua. Penentuan Komponen Kimia Dan Kandungan
Gizi Pada Buah Merah. Diakses tgl 19 Juli,2008 pukul 20 : 21 Wit di Makassar.
Sudarmadji, S., dkk,1989, Analisa Bahan Makanan Dan Komponen Kandungan Kimia.
Liberty, Yogyakarta.
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN Halaman
1.1. Latar Belakang…………………………………………………………... 1
1.2. Maksud………………………………………………………………….. 2
1.3. Tujuan……………………………………………………………………. 2
1.4. Manfaat………………………………………………………………….. 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1.Pengenalan Buah Merah…………………………………………………. 4
2.2. Cara Memilih Buah Merah………………………………………………. 4
2.3.Habitat…………………………………………………………………….. 5
2.4. Kemurnian Produk……………………………………………………….. 6
BAB III METODE PENELITIAN 7
3.1.Metode Penelitian………………………………………………………….7
3.2 Cara mengolah Buah Merah……………………………………………... 7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 8
4.1.1.Zat-zat komponen kimia yang terkandung pada buah merah………… 8
a.senyanwa anti oksida……………………………………………… 8
b.Betakaroten……………………………………………………….. 8
c. Tokoferol………………………………………………………… 9
d.Asam lemak………………………………………………………. 9
4.1.2 Kandungan Komponen Kimia Pada Buah Merah…………………… 10
Tabel 1. KomposisiKandungan Kimia……………………………………. 10
Tabel 3. Daftar komposisi gizi pada buah merah……………………………11
4.1.3 Pembahasan …………………………………………………………. 11
BAB V KESIMPULAN 12
Kesimpulan……………………………………………………………………… 13
DAFTAR PUSTAKA 14
ANALISIS KOMPONEN KANDUNGAN KIMIA PADA BUAH MERAH
(Pandanus Conoideus. Lam)
Oleh
Yusuf Pekei
H31 106 205
JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERTSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009
Langganan:
Postingan (Atom)